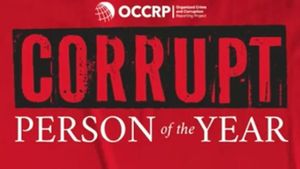JAKARTA - Kasus COVID-19 di Indonesia telah menyentuh angka dua juta. Hari ini, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat angka rinci 2.033.421, dengan kasus aktif 160.524. Ini adalah ledakan meski tak seharusnya jadi kejutan. Seberapa dekat kita dengan titik terburuk?
Pada Rabu sore, 23 Juni, Kemenkes mengumumkan 15.308 kasus positif COVID-19 baru. Angka itu didapat dari pemeriksaan 141.187 spesimen. Kemenkes juga mencatat 303 kematian sehingga total korban wafat akibat COVID-19 mencapai 55.594 jiwa.
Seperti hari-hari sebelumnya DKI Jakarta tetap provinsi yang catat kasus harian terbanyak. Hari ini terdata 4.693 sehingga total kasus di Jakarta menjadi 486.957. Setelah Jakarta ada Jawa Barat dengan 2.910 kasus baru, Jawa Tengah (2.595) dan Jawa Timur (873).
Yang paling dikhawatirkan dari ledakan kasus adalah ambruknya kemampuan fasilitas kesehatan. Itu sudah terjadi. Kapasitas tempat tidur di 106 rumah sakit rujukan COVID-19 DKI Jakarta telah mencapai 90 persen. Sementara, kapasitas ICU telah mencapai 81 persen.

"Tempat tidur sampai 90 persen ... ICU 81 persen, kami terus melakukan penambahan TT (tempat tidur). Dan ruang ICU," kata Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 22 Juni.
Jika ditarik lebih luas se-Pulau Jawa, kegawatan ini juga nampak merata. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan bed occupancy rate (BOR) di seluruh provinsi Pulau Jawa telah mencapai 80 persen, kecuali Jawa Timur yang angkanya 66,67 persen.
Merinci data itu, BOR Jawa Barat menyentuh 86,36 persen; Jawa Tengah 86,16%; DIY 83,39%; Banten 82,77%. Lalu seberapa parah ledakan kasus ini? Merujuk data yang sama, secara nasional Indonesia mengalami peningkatan kasus mingguan hingga 92 persen sejak empat pekan terakhir.
Dalam ilustrasi lebih sederhana, satu dari dua orang di sekeliling kita telah mengidap COVID-19. Per Selasa, 22 Juni, angka positivity rate COVID-19 di Indonesia telah mencapai 51,62 persen.
“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” begitu ucap Wiku, Selasa, 22 Juni.
Ledakan tak seharusnya jadi kejutan

Benar, ini adalah ledakan. Tapi tak seharusnya jadi kejutan. Reaksi keterkejutan yang kita lihat hari ini, terutama dari sisi pemerintah tak lebih dari bukti penanganan pandemi di negeri ini dilakukan dengan pendekatan reaktif. Tak terskema dalam sebuah grand design yang terang dan terukur.
Pertumbuhan kasus selalu bisa diprediksi. Meski mustahil seratus persen akurat, selalu ada pemodelan yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan strategi pengendalian pandemi. Apakah itu dilakukan?
Epidemiolog Griffith Univesity, Australia, Dicky Budiman menyoroti pola kebijakan pandemi yang tak berlandaskan sains oleh pemerintah Indonesia. Kecolongan dalam memantau pertumbuhan kasus adalah bukti.
"Secara keilmuan ya bisa diprediksi. Estimasi kasar tapi ya. Tapi akan tetap membantu dengan range yang relatif enggak jauh lah. Itu bisa jadi landasan strategi untuk mengantisipasi. Kan prediksi-prediksi dan skenario terburuk itu untuk meningkatkan respons supaya tidak terjadi. Jadi mitigasi respons," Dicky kepada VOI, Rabu, 23 Juni.
Banyak yang menganggap ledakan kasus hari ini sebagai dampak dari pergerakan manusia di musim Lebaran. Mungkin saja. Versi lain, pemerintah menyebut varian baru COVID-19 Delta jadi biang kerok ledakan kasus. Bisa jadi. Tapi ada masalah lain yang lebih gawat.
Ledakan kasus hari ini bisa jadi lebih luas sebagai akumulasi dari kesalahan-kesalahan penanganan selama satu tahun. "Saya pernah memprediksi di awal tahun bahwa dalam enam bulan pertama 2021 ini kita akan mengalami masa yang sangat kritis."
"Karena kritis tiga bulan pertama itu adalah respons untuk mencegah. Karena gelombang ini kan akan meningkat menuju puncak. Dan itu adalah akumulasi satu tahun. Jadi bisa diprediksi titik jenuhnya akan tercapai di Juni-Juli. Itu ancer-ancernya."

Kita perlu kembali ke April 2020 untuk mendalami logika pemodelan Dicky. Saat itu World Health Organization (WHO) menetapkan situasi pandemi COVID-19 Indonesia telah mencapai level community transmission atau penularan lokal. Itu adalah sirine paling buruk pertama sepanjang peperangan kita melawan penyebaran virus ini.
Dalam level community transmission, otoritas --negara, kota atau negara bagian-- idealnya menetapkan lockdown total. Fiji, Brisbane, hingga Gaza menerapkan lockdown total ketika mereka menyentuh level itu. Ada konsekuensi, tentu saja. Biasanya ekonomi.
[JURNALISME RASA: Pengetahuan dan Teori Konspirasi COVID-19 di Kepala Masyarakat Desa]
Kebimbangan itu dialami semua otoritas di dunia. Tapi pandemi adalah peperangan yang membutuhkan kebijakan-kebijakan tegas dan cepat. Semakin larut, semakin luas penularan, semakin sulit dikendalikan, semakin habis pilihan-pilihan langkah yang memungkinkan.
Ujungnya, langkah-langkah pemulihan akan makin berat. Tak cuma segi kesehatan tapi juga aspek ekonomi. Iya, melihat masalah pandemi hari ini adalah mengungkit kebijakan-kebijakan lama. Pandemi adalah marathon yang finishnya ditentukan oleh kita sendiri.
"Lalu respons pemerintahnya makin bagus, kuat, puncaknya itu cepat tercapai, cepat landai. Yang bagus begitu. Jadi kalau ada satu negara gelombangnya panjang, lama, itu berarti enggak berhasil intervensinya."
"Indonesia kan dalam level community transmition sudah sejak April 2020 sampai sekarang. Artinya kan banyak kasus infeksi dan klaster ini enggak terdeteksi sehingga terus berkembang, beranak pinak si kasus ini."
Seberapa dekat yang terburuk dan bisa apa kita?

Seorang perempuan berdoa di pemakaman khusus COVID-19 di Srengseng Sawah (Sumber: Antara)
Satu kaki kita sudah di tengah badai. Kita berada di posisi silent outbreak. Hari-hari ke depan akan lebih genting dan terasa mengerikan seiring masifnya tes yang berimplikasi pada temuan kasus dan masuknya orang-orang ke fasilitas kesehatan. Semua perlu fokus.
Pemerintah harus mengembalikan orientasi penanganan pandemi pada kesehatan. Tak ada cara lain. Tracing, testing, and treatment (TTT) dan vaksinasi tentunya harus digeber. Di sisi masyarakat, kesadaran bahwa pandemi belum selesai harus terus dijaga. Menjaga diri dan keluarga serta orang dekat jadi kewajiban.
Dan yang juga penting, berhenti saling tunjuk kesalahan antara masyarakat. Kita semua korban dari kesalahan-kesalahan pemerintah. Sebagaimana dipaparkan dalam artikel BERNAS berjudul Demo Madura: Tak Percaya COVID atau Skeptisme Kebijakan Pandemi? kritik terarah jadi penting.
Pandemi terlalu menyerap energi. Silakan alokasikan energi ke titik yang tepat. Pemerintah suka tak suka adalah pihak yang memiliki segala instrumen dan sumber daya penanganan pandemi. Karenanya, menjaga pemerintah tetap di jalur yang benar lewat kritik adalah bentuk kontribusi publik.
Kembali ke konteks puncak pandemi hari ini, ada beberapa pemodelan yang menunjukkan seberapa dekat kita dengan yang terburuk. Pertama dari demografi. Indonesia didominasi masyarakat muda. Mobilitasnya cenderung lebih tinggi. Implikasinya pada transmisi virus.
Pemodelan kedua adalah dengan memantau berkala pertumbuhan. Pantauan pertumbuhan kasus yang dilakukan Dicky menempatkan waktu antara Juni dan Juli sebagai masa terburuk. "Dengan angka pertumbuhan itu, misalnya 5 persen, 10 persen, itu kan akan mencapai titik jenuh."
"Ketika klaster itu terus bergerak dan akhirnya menuju kelompok paling rawan di populasinya, lansia, faktor risiko, di situlah meledak. Nah yang disebut puncak tuh begitu. Meledak, banyak sekali kasusnya. Faskes kewalahan."
Butuh langkah radikal daripada sekadar PPKM Mikro

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memilih PPKM Mikro sebagai kebijakan pengendalian situasi pandemi hari ini. Ini sekaligus membantah dorongan banyak pihak agar pemerintah mengambil langkah lockdown.
"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah," kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu, 23 Juni.
Hermawan Saputra, anggota dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menilai pemerintah perlu langkah lebih radikal ketimbang PPKM Mikro. Selain klaster-klaster yang tak terselesaikan, Indonesia juga dibebani dengan virus corona varian Delta yang menular lebih cepat.
PPKM Mikro, menurut Hermawan tak akan menyelesaikan persoalan karena pencegahannya tidak menyeluruh di satu wilayah, melainkan hanya di tatanan kecil, yaitu RT dan RW. Ada dua opsi yang ditawarkan Hermawan: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina wilayah.
PSBB dapat dilakukan terbatas di pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatra, juga Kalimantan. Sementara, karantina wilayah akan berimplikasi pada penutupan bandara, transportasi lokal, hingga pengawasan ketat terhadap aktivitas di dalam wilayah. "Situasi saat ini sangat berbeda," kata Hermawan.
"Jika pemerintah menunda-nunda (pengambilan langkah radikal), kerugian akan terus bertambah, ekonomi tidak akan pulih, dan kesehatan masyarakat terkatung-katung," tambah dia, dikutip DW, Rabu, 23 Juni.
*Baca Informasi lain soal COVID-19 atau baca tulisan menarik lain dari Diah Ayu Wardani, Ferdinan, Wardhany Tsa Tsia dan Yudhistira Mahabharata.