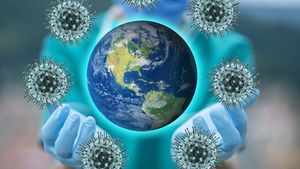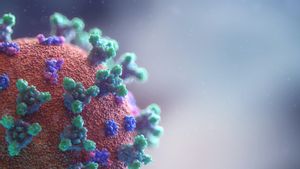JAKARTA - Warga Madura berdemo di Balai Kota Surabaya. Aksi ini disoroti karena potensi penularan. Di waktu yang sama, pecah opini terjadi. Beberapa narasi yang menguat menyudutkan aksi massa itu dengan cap 'kebodohan'. Padahal jika mendalami persoalan, aksi massa ini bukan cuma soal percaya atau tak percaya COVID-19 tapi tentang skeptisme pada kebijakan pandemi.
Kita dalami tuntutan demonstran. Ada tiga. Pertama agar pemerintah Kota Surabaya menghentikan penyekatan diskriminatif di jalur lintas Jembatan Suramadu. Dalam kebijakannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pemerintah Kabupaten Bangkalan menghentikan pergerakan warga Madura masuk Surabaya tanpa swab tes.
”Sejak 6 Juni masyarakat Madura dipasung oleh kebijakan penyekatan dan swab antigen di Suramadu setiap hari. Pemerintah Kota Surabaya minta kepada Bupati Bangkalan agar tidak membiarkan atau melarang warga masuk ke Surabaya tanpa swab."
"Ini saya baca dari salah satu media. Eri Cahyadi hanya ingin melindungi warga Surabaya tanpa melihat dampak yang dirasakan warga Madura, utamanya sektor ekonomi,” ungkap Ahmad Annur dari Koalisi Masyarakat Madura Barsatu di lokasi aksi.
Tuntutan kedua, demonstran mendorong agar pemberlakuan swab test digeser ke tempat-tempat hiburan dan sumber kerumunan lain di Surabaya. Ketiga mereka menuntut Eri Cahyadi meminta maaf kepada warga Madura.

Sebelum menggeruduk Balai Kota Surabaya, massa juga merusak posko penyekatan Suramadu. Perusakan Posko Suramadu terjadi pada Jumat, 18 Juni dini hari. "Mereka rata-rata tergesa-gesa mau bekerja dan berangkat sebelum shubuh."
"Lalu di sini ada penumpukan sehingga harus menunggu. Nah, saat itu ada yang tidak sabar dan ingin cepat-cepat sampai yang lain terpengaruh," ujar Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Irvan Widyanto, 18 Juni.
Sebelumnya, beberapa video perusakan posko penyekatan Suramadu sisi Surabaya viral di sejumlah media sosial. Dalam video tersebut, meja dan kursi sudah berserakan dan sejumlah dokumen berhamburan.
Beberapa petugas dan tenaga kesehatan tak kuasa membendung warga. Mereka menyelamatkan diri. Sejumlah aparat TNI-Polri tampak mencoba menenangkan warga di lokasi. Tak lama, keadaan kemudian terkendali.
#suramadu klau kayak gini kemungkinan ada klaster baru😄😄😄 pic.twitter.com/0BFk1zkxcG
— tante kesepian (@Jono68535970) June 18, 2021
Pentingnya kritik terarah
Selasa, 22 Juni, kata "Herd Stupidity" dan "Madura" sempat jadi trending topic di Twitter. Bahasan itu didominasi kritik terhadap aksi demonstrasi massa di Balai Kota Surabaya. Warganet juga melihat aksi itu sebagai penyangkalan masyarakat Madura terhadap COVID-19.
welcome Herd Stupidity
kaum covidiots pasti bersukaria 🎇🎆 https://t.co/k4dPNRvXhx
— #TT Dewi Darmawati (@dewi_darmawati) June 21, 2021
"Herd Stupidity" adalah istilah yang pertama kali diucap oleh epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono. Di akun Twitternya, Pandu mengkritisi perilaku masyarakat luas yang mengabaikan upaya-upaya pengendalian pandemi, khususnya pada aktivitas mudik Lebaran 2021.
Kata-kata Pandu itu yang kemudian dikaitkan dan diangkat dalam banyak narasi menyoal demonstrasi masyarakat Madura. Amat relevan memang dalam banyak hal. Namun belum tentu tepat jika warganet mengaitkannya dalam konteks demonstrasi Madura.
Indonesia sudah lama dalam kondisi "Herd Stupidity". Perilaku Manusianya yg dorong replikasi virus , memperbanyak diri dan berubah menjadi lebih mudah menular. Manusia yg mendapat amanah jadi pejabat dan manusia-manusia lain yg tidak berperilaku 5M & enggan divaksinasi. pic.twitter.com/sDPSESJJZ8
— Juru Wabah 🇮🇩 (@drpriono1) June 20, 2021
Masyarakat saling menyalahkan. Di sisi lain pemerintah terus mengulang kesalahan yang sama: inkonsisten dan menyimpang dari konsep pengendalian pandemi berbasis sains. Dalam hal ini kritik yang terarah jadi penting. Kenapa harus selalu pemerintah yang dikritik?
Iya, pengendalian pandemi adalah tanggung jawab semua orang. Tapi pemerintah lah yang memiliki segala instrumen dan sumber daya dalam upaya-upaya pengendalian pandemi. "Pemerintah. Yang punya otoritas itu pemerintah," ungkap epidemiolog Griffith Univesity, Australia, Dicky Budiman kepada VOI, Selasa, 22 Juni.

Dicky menyebut setidaknya tiga kesalahan berulang yang terus dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tiga kesalahan itu adalah inkonsistensi dalam penerapan strategi, komunikasi risiko kepada masyarakat yang tak terkelola baik serta yang paling mendasar: kebijakan tak berlandaskan sains.
"Karena adanya sifat skeptis dari masyarakat ini (disebabkan) terlalu berlarut-larut pandemi kita ini. Berlarut tidak terkendali. Dan inilah contoh nyata dari dampak negatif pandemi yang tidak fokus pada kesehatan. Dan mereka jadi abai," tutur Dicky.

Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah, Tantan Hermansah menyoroti sisi dinamika sosial. Menurut Tantan peristiwa demonstrasi massa di Madura dan beberapa tempat lain, termasuk Bandung merupakan ledakan akumulasi dari skeptisme publik pada langkah penanganan pandemi oleh pemerintah.
"Mereka sudah mulai lelah dengan skenario pemerintah dalam mengelola pandemi ini. Mereka membaca bahwa pemerintah dengan peristiwa ini alih-alih jelas dan benar menangani bencana, yang ada malah mengharu biru masyarakat dengan 'mengail di air keruh'," tutur Tantan kepada VOI, Selasa, 22 Juni.
"Meski ini bisa jadi sangat bisa dibantah, namun dengan sumberdaya yang kuat, pemerintah justru seperti membiarkan saja asumsi tersebut mengkristal di masyarakat. Akibatnya ketidakpercayaan kecil berkoneksi dengan wacana yang melegitimasinya, maka yang terjadi kemudian adalah ekspresi massa."
Lantas bagaimana seharusnya?
Pertama tentu saja tak perlu terpolarisasi dalam sikap saling menghakimi. Kita, masyarakat sama-sama korban dari pengelolaan pandemi yang keliru. Dasarnya satu, otoritas tak pernah benar-benar memandang masyarakat sebagai subjek dalam kebijakan-kebijakan pengendalian pandemi.
"Masyarakat ini bukan objek. Saya selalu mengingatkan masyarakat ini adalah subjek. Jadi mereka harus punya pemahaman yang sama. Selama ini saya lihat masyarakat dijadikan objek. Itu yang berbahaya dan salah tentu. Ini akarnya," ungkap Dicky Budiman, epidemiolog Griffith University.
Apa maksud Dicky? Dalam perspektif masyarakat sebagai subjek, pengendalian pandemi adalah seni menumbuhkan gerakan massal. Kesadaran dan partisipasi publik harus dibangun. Modalnya kepercayaan. Transparansi jadi hal terpenting di setiap pengambilan kebijakan.
Bahkan keterbatasan pemerintah bukan masalah ketika transparansi dikedepankan. "Tapi ini harus dibuka kemampuan pemerintah ini. Kita punya ini, strateginya ini, konsekuensinya apa. Pun dengan keterbatasannya. Dibuka saja. Ini untuk pemerintah daerah dan pusat agar masyarakat bisa menilai."
"Akhirnya masyarakat enggak ngerti situasi sebenarnya seperti apa, tiba-tiba melonjak. Kan pemerintah sebelumnya bilang tadinya baik, tadinya efektif. Jadi ya transparansi data, manajemen pengendalian pandemi kita, strategi komunikasi risiko," tutur Dicky.

Dari sisi sosiologis, Tantan Hermansah, sosiolog UIN Syarif Hidayatullah berpendapat sama bahwa masalah kepercayaan yang tak terbangun ini sebagai akar dari situasi ketidakpatuhan publik hari ini.
Menurut Tantan pemerintah harus membuat skenario berbasis grand design. Masyarakat memerlukan gambaran soal rencana yang runut, sistematis dan masuk akal tentunya. Dan kebijakan itu harus disosialisasikan dengan gencar.
"Yang dibaca oleh masyarakat saat ini adalah skenario tambal sulam saja. Saya melihat bahwa pandangan ini tervalidasi dengan kebijakan-kebijakan temporal seperti PSBB dan PPKM. Di mana semakin lama, kebijakan ini malah tidak menunjukkan tajinya dalam konteks pengendalian pandemi," Tantan.
"Sebenarnya ini bukan murni penolakan. Sebab kalau mereka jelas menolak, kenapa tidak dari dulu. Ini menjadi semacam pesan simbolik, 'Yuk pemerintah yang benar dong mengurusi rakyat selama pandemi ini.'"
*Baca Informasi lain soal COVID-19 atau baca tulisan menarik lain dari Ferdinan dan Yudhistira Mahabharata.