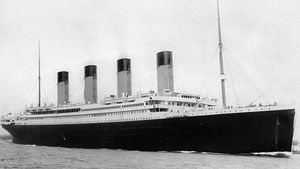JAKARTA – Sejarah hari ini, 84 tahun yang lalu, 24 Juni 1939, pejuang kemerdekaan, Soekiman Wirjosandjojo suarakan nasib buruh --utamanya buruh bumiputra-- di Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa Swiss. Ia mengungkap nasib buruh di Hindia Belanda (kini: Indonesia) kian nelangsa.
Kondisi itu diperparah dengan kewenangan tuan tanah memberikan hukuman pukul dan kurungan. Ia meminta kepada seluruh negara di dunia untuk turun membantu kaumnya. Sebelumnya, pemerintah kolonial bak memanfaatkan perburuhan sebagai perbudakan tersebulung.
Urusan menyengsarakan kaum bumiputra, pemerintah kolonial Hindia Belanda jagonya. Empunya kuasa ingin kaum bumiputra dapat dimanfaatkan dalam skala besar. Keinginan itu kerap digaungkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van den Bosch.
Ia melihat pemerintahannya punya kuasa untuk itu. Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel pun dilanggengkan. Belanda untung, penguasa lokal – dari bupati hingga kepala desa—kaya raya. Satu-satunya yang rugi adalah segenap kaum bumiputra jelata.
Mereka diperas bak sapi perah. Belanda memaksa mereka menanam tanaman produktif untuk keperluan ekspor. Kemudian, membelinya dengan harga semurah mungkin. Sistem tanam paksa itu bertahan hingga 40 tahun (1830-1870).

Golongan liberal dan humanis Belanda jadi yang paling bersuara keras supaya diakhirinya sistem tanam paksa. Perjuangan itu berhasil. Namun, tabiat Belanda memeras kaum bumiputra tak pernah berakhir. Belanda kemudian memberikan hak pengusaha Belanda untuk menjalankan bisnisnya di Nusantara.
Kuasa itu membuat pengusaha Belanda menjadikan kaum bumiputra sebagai buruh murah. Mereka kerap mendapatkan upah kecil. Pun tuan tanah tempat mereka bekerja tak segan-segan menghukum jika ada kesalahan dari buruh. Hukuman pukul maupun kurungan.
“Penderitaan bangsa Indonesia hanya sedikit dikurangi. Taraf kehidupan mereka tetap rendah. Dengan begitu penghapusan Cultuurstelsel tidak berarti datangnya kemakmuran (taraf hidup lebih dari cukup) pada bangsa Indonesia. Tingkatan hidup rakyat Indonesia dipertahankan tetap rendah, supaya mudah mencari buruh yang murah.”
“Industrialisasi tidak dikembangkan secara meluas supaya tidak merugikan industri Belanda yang tidak timbul kelas (serikat) buruh yang kuat. Sifat masyarakat pribumi yang agraris dipertahankan dan dijaga jangan sampai timbul kelas menengah pribumi (borjuis nasional),” ungkap G. Moedjanto dalam buku Indonesia Abad Ke-20 Jilid 1 (1989).
Nelangsanya kehidupan kaum buruh dirasakan oleh segenap pejuang kemerdekaan. Soekiman, apalagi. Pria yang pernah menjadi pimpinan Perhimpuan Indonesia (PI) di negeri Belanda melihat kaum buruh harus dibela. Ia kemudian jadi pimpinan buruh pegadaian.
BACA JUGA:
Kuasa itu membuat Soekiman berkesempatan menjadi tamu dari Konferensi Perburuan Internasional di Jenewa, Swiss. Ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia berpidato membela kepentingan buruh bumiputra pada 24 Juni 1939.
Pria yang kemudian menjelma sebagai Perdana Menteri Indonesia (1951-1952) mengajak segenap hadirin untuk memikirkan nasib dan mendukung buruh bumiputra mendapatkan upah yang layak. Ia juga meminta mereka untuk membantu buruh tak diperlakukan bak perbudakan terselubung.
“Soekiman memaparkan bahwa kaum buruh pribumi di Indonesia, tidak berdaya dan tidak mempunyai pelindung. Mereka tidak memiliki organisasi buruh yang tersusun baik, dan tidak mempunyai partai politik. Seperti di Eropa dan Amerika yang dapat membela kepentingan kaum pekerja di parlemen.”
“Soekiman mengungkap Rakyat kami dalam banyak hal masih terbelakang, karena itu berhak untuk mendapat santunan khusus dari lembaga seperti International Labour Organisation (ILO) yang memang didirikan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup dan memperbaiki kelemahan sosial di antara kaum buruh, terutama untuk buruh pribumi," ujar Lukman Hakiem dalam buku Soekiman (2022).