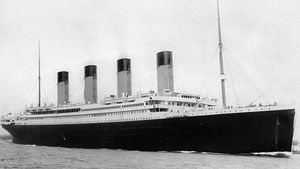JAKARTA – Sejarah hari ini, 403 tahun yang lalu, 26 Juni 1620, Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Coen mengeluh kepada petinggi Kompeni di Amsterdam, Belanda. Ia mengeluh jumlah budak yang tinggal di Batavia (kini: Jakarta) meningkat tajam.
Populasi budak itu membuat Coen khawatir akan potensi mereka mengganggu moral dan keamanan Batavia. Sebelumnya, Kompeni kerap menyanjung tinggi bisnis perbudakan. Bisnis itu banyak membantu Kompeni membangun koloni. Apalagi, bisnis perbudakan buat VOC untung bejibun.
Tiada yang meragukan hasrat Kompeni memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Mereka melanggengkan segalanya untuk meraih kuasa. Dari perang hingga adu domba. Kuasa itu membuat Kompeni ‘menyulap’ Jayakarta jadi Kota Batavia (kini: Jakarta) sebagai pusat kekuasaannya.
Hasilnya gemilang. Kekuasaannya di tanah Nusantara mendapatkan titik cerah. Namun, Kompeni mulai sadar diri. Mereka tak dapat bekerja seorang diri. Keinginan Kompeni mendatangkan suku bangsa lain ke Batavia mengemuka.
Keinginan itu awalnya terarah kepada orang China. Kerja keras dan keuletan orang China jadi musababnya. Apalagi, di era pemerintahan Jan Pieterszoon Coen. Gubernur Jenderal VOC yang pernah menjabat dua kali (1619-1623 dan 1627-1629) itu membukakan pintu lebar-lebar supaya orang China menggerakkan roda ekonomi Batavia.

Opsi itu berhasil, tapi belum cukup. Kompeni pun putar otak dengan mulai mendatangkan banyak budak untuk membantu segala macam pekerjaan tuan kulit putih. Budak didatangkan karena mereka dianggap tenaga kerja paling murah.
Budak dapat bekerja dalam segala macam pekerjaan. Apalagi mereka dapat membangun apa saja. Andai ada budak yang tak sesuai dengan hasrat membangun Kompeni, empunya kuasa bisa menjual budak kepada tuan tanah lainnya yang membutuhkan. Hasil jual budak itu kemudian membuat VOC untung bejibun.
“Selain warga Asia Tenggara, Eropa, dan China, masih ada kelompok juragan budak lainnya yaitu Kompeni (VOC) yang lebih mementingkan tersedianya tenaga buruh yang murah. Sejujurnya, tanpa adanya para budak maka benteng serta kubu pertahanan Kompeni tidak akan dapat dibangun.”
“Demikian sudah disimpulkan pada 1615 oleh penguasa (Gubernur Jenderal VOC) Gerard Reynst. Seorang budak dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan ketimbang dua orang Belanda, sebab udara panas dan minuman keras terlalu banyak beredar di mana-mana,” ungkap sejarawan Hendrik E. Niemeijer dalam buku Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII (2012).
Perbudakan di Batavia pun berkembang pesat. Saban hari budak dari berbagai wilayah dari luar negeri dan luar Nusantara berdatangan. Kondisi itu membuat Batavia sempat dijuluki Kota Budak. Julukan itu karena budak hadir dalam setiap sendi ekonomi kota.

Namun, perkembangan itu justru membuat khawatir peletak dasar kolonialisme Nusantara, Jan Pieterszoon Coen. Kehadiran budak dianggap justru jadi bumerang bagi kuasa Belanda di Batavia. Sebab, banyak budak yang tak memiliki banyak keahlian berpotensi mengganggu banyak hal.
Alih-alih hanya mengganggu keamanan, kehadiran budak, utamanya wanita dapat merusak moral orang Belanda. Banyak orang Eropa jadi terpaksa menikah dengan budak yang dianggap rendah. Karenanya, banyak lahir anak-anak yang tak diinginkan -- tindakan aborsi pun kadang dilanggengkan. Ia pun menulis surat khusus berisi keluhan terkait ramainya budak di Batavia kepada petinggi VOC di Amsterdam, Belanda, 26 Juni 1620.
BACA JUGA:
“Semua budak itu biasanya diangkut ke Batavia, sehingga benteng VOC yang tak seberapa luas itu – lokasinya kini berada di sekitar gedung Pantja Niaga, Jalan Roa Malaka, Jakarta Kota bertambah padat populasinya.”
“Jan Pieterszoon Coen, dalam sebuah suratnya tanggal 26 Juni 1620, kepada direksi VOC di Amsterdam mengeluh, jumlah budak dan warga kota bebas (vrije borger), yaitu orang Eropa yang bukan serdadu Kompeni di permukiman bentengnya, mencapai dua ribu orang. Ini menandakan meningkatnya jumlah budak,” tertulis dalam laporan Majalah Tempo berjudul Lembar-Lembar Perbudakan di Batavia (1985).