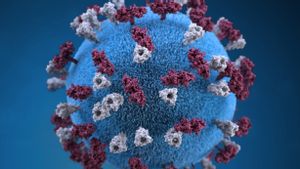JAKARTA - Virus corona mungkin tak pilih-pilih. Pun dengan penyakit yang disebabkannya, COVID-19 yang tak pandang bulu. Namun, perkara dampak, beda lagi. Pandemi jelas persoalan kelas sosial. COVID-19 lebih petaka bagi orang miskin, kaum pinggiran, dan segala masyarakat kelas bawah. Sedang untuk kalangan atas, COVID-19 jauh lebih 'tertangani.' Jangan dulu mengutuk. Mari belajar dari kasus positif COVID-19 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pagi hari, 1 Desember, telepon genggam kami sudah sibuk. Notifikasi sahut-sahutan. Sumbernya dari ruang percakapan yang sama: grup redaksi kantor. "Anies positif," tulis seorang reporter lapangan yang disusul sebuah video pernyataan Anies.
Dalam pernyataan di video yang dikirim secara resmi oleh Pemprov DKI Jakarta itu, Anies menjelaskan protokol demi protokol yang ia lakukan dalam keseharian, termasuk rutin tes usap atau swab test. Ada beberapa rangkaian swab test yang krusial sebelum Anies dinyatakan positif. Pertama, tes pada Rabu, 25 November lalu. Saat itu hasil tes Anies negatif.
Setelah itu Anies mendapat kabar bahwa Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria tertular COVID-19 dari staf pribadinya, Anies melakukan tes usap antigen pada 29 November. Hasilnya juga negatif. Namun, 30 November Anies kembali menjalani tes usap PCR untuk mengonfirmasi hasil antigen hari sebelumnya. Malam di hari itu Anies mendapat kabar hasilnya positif.
Lewat video itu Anies juga mengimbau semua orang yang berinteraksi dengannya dalam beberapa hari terakhir melakukan tes usap PCR atau isolasi mandiri. "Bagi siapapun yang pernah ketemu saya silakan hubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap. Tim tracing Dinkes akan mendata, menghubungi semua kontak erat, dan seluruh prosedur terkait akan dijalankan," kata Anies.
Kita sepakat, COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Termasuk Anies. Bagi Anies, sebagaimana penjelasannya, protokol bisa ia jalani dengan lancar. Rangkaian swab test, bahkan protokol lanjutan pasca-dirinya dinyatakan positif. Bagi yang lain, belum tentu seperti itu.
Petaka kelas bawah
Pandemi adalah persoalan kelas. Sifatnya tak lagi dapat dilihat dari sekadar siapa terjangkiti dan siapa yang tidak. Bicara pandemi, maka kita perlu menyoroti banyak faktor lain, seperti akses kesehatan, informasi, bahkan rangkaian kebijakan lain yang diambil sebuah negara, termasuk pengelolaan anggaran.
Dampak pandemi bagi masyarakat kelas bawah lebih destruktif. Goncangan kelas yang diakibatkan COVID-19 membuat mereka makin terhimpit, baik secara sosial maupun ekonomi.
Max Weber, salah satu pendiri ilmu sosial telah memberi landasan kuat untuk melihat bencana pandemi COVID-19 dari aspek ketidakseimbangan struktural terkait kelas, status, dan kekuasaan. Ia memberi kerangka analisis kelas --yang banyak dijadikan referensi saat ini-- dengan membagi kelas menjadi tiga bagian: bawah (lower class), menengah (middle class), dan atas (upper class).
Seperti diketahui, struktur sosial-ekonomi penduduk Indonesia masih didominasi kelas bawah dan menengah. Menurut data yang dipaparkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai 60 juta orang pada 2019.
Secara teoritis, jumlah kelas bawah bisa jadi hampir dua kali lipat dari angka kelas menengah. Bahkan menurut Bank Dunia (2020) proporsi kelas bawah di Indonesia mencapai 79 persen, kelas menengah 20 persen, dan kelas atas jumlahnya hanya kurang dari satu persen.
Direktur Program dan Riset The Habibie Center, Mohammad Hasan Ansori, dalam tulisannya yang bertajuk Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia menjelaskan persoalan pandemi dan kelas sosial di negeri ini lebih spesifik. Ia menjelaskan masyarakat kelas bawah di Indonesia lebih rentan dan berisiko terkena dampak pandemi.
Penyebabnya, masyarakat kelas bawah tidak memiliki ketahanan sosial yang lebih baik. Kondisi ini, kata Hasan dapat berkepanjangan jika merujuk pada masa trauma pascabencana. Mirisnya, sejauh ini belum ada data yang menggambarkan kategori kelas sosial-ekonomi para pasien yang terpapar COVID-19.
Bahkan, di Jakarta, di mana kasus COVID-19 paling banyak, otoritas hanya bisa menggambarkan variabel gender dan usia para pasien. Padahal data soal kelas sangat penting, setidaknya untuk mendistribusikan bantuan agar bisa mengurangi beban ekonomi kelas-kelas tertentu dalam situasi pandemi.

Selain itu, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi pergerakan masyarakat secara ketat --kecuali untuk keperluan esensisal seperti ekonomi-- telah memukul dan berdampak secara masif terhadap ekonomi masyarakat kelas bawah, terutama pekerja di sektor informal dan atau pekerja harian. Dalam hal ini, kata Hasan, tidak keluar rumah dapat memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda untuk setiap kelas. Bagi masyarakat kelas bawah, tidak keluar rumah dapat berarti tidak bisa makan sama sekali di hari tersebut.
Senada. Sosiolog Universitas Islam Nasional (UIN) Syarif Hidayatullah, Tantan Hermansyah mengatakan pandemi menyebabkan kondisi ekonomi golongan kelas bawah makin terhimpit. Faktor penyebab paling signifikan adalah bagaimana pandemi menyebabkan guncangan pada setiap kelas sosial, bukan cuma kelas bawah.
Pandemi menyebabkan mereka yang ada di kelas atas mulai melorot ke kelas menengah. Lalu yang berada di kelas tengah, meski masih banyak yang bertahan, tak bisa dipungkiri juga mengalami penurunan kelas sosial. Lantas bagaimana yang berada di kelas bawah?
"Ini yang paling menderita," kata Tantan kepada VOI, Selasa, 1 Desember. "Sudah kue ekonomi di kelas ini sangat terbatas, sekarang mereka harus berebutan peluang dengan mereka yang tadinya ada di kelas atasnya," tambah Tantan.
Di sinilah peran negara. Pemerintah harus mampu menopang masyarakat kelas bawah lewat pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk memberi mereka kekuatan yang sama untuk menangani berbagai persoalan di tengah pandemi. Pemerataan akses kesehatan lewat swab test yang tak cuma terjangkau tapi juga gratis, yang tak cuma gratis tapi juga terjangkau jadi tanggung jawab yang harus dipenuhi pemerintah.
Biaya swab test jadi masalah
Salah satu sebab mengapa upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 ini bagai mencincang air adalah biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk melakukan swab test. Permasalahan ini bukan hanya menghambat penanganan pandemi, tapi juga menyengsarakan kehidupan mereka.
Kisah Ervina Yana, seorang ibu hamil di Makassar, Sulawesi Selatan jadi gambar kegagalan negara melindungi warganya. Dilaporkan BBC, Ervina kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp2,4 juta. Padahal saat itu ia membutuhkan tindakan cepat untuk operasi kehamilan.
Pemerintah, per 5 Oktober lalu memang telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang batas biaya maksimal tes PCR COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, batas biaya maksimal tes PCR mandiri adalah Rp900 ribu. Masih tergolong tinggi. Sebagai perbandingan, India. Saat ini pemerintah India menetapkan harga paling mahal swab test di angka Rp468.000, seperti dikutip Bisnis.
Kemenkes lewat SE tersebut mengakui ada masalah dalam harga tes PCR, terutama soal ketidakpastian harga. Karenanya dibutuhkan penyeragaman.
"Pemeriksaan RT-PCR yang dilakukan oleh rumah sakit atau laboratorium saat ini memiliki tarif yang bervariasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi seluruh pihak terkait dalam pelayanan pemeriksaan RT-PCR. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah perlu menetapkan standar tarif pemeriksaan RT-PCR dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen lainnya," tertulis dalam surat yang terbit berbulan-bulan setelah Ervina kehilangan kandungannya pada Juni.

Sayang, penyeragaman di angka Rp900 ribu tetap bukan solusi berkeadilan. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mendorong agar pemerintah menggratiskan biaya tes COVID-19. Dan tak sekadar gratis, tapi juga merata untuk semua. Selain untuk melindungi masyarakat kelas bawah, bagaimanapun tes adalah ujung tombak untuk menangani pandemi, sebagaimana rumusan 3T yang kerap disosialisasikan (tracing, testing, treatment).
"Harusnya, (tes) dilakukan secara masif, dan karena di situlah kita tau sejauh mana tingkat perkembangan penularan COVID-19 ... Harusnya tes itu gratis semuanya," kata Trubus kepada VOI.
Di pemerintah pusat ada penyeragaman tarif, di Jakarta ada penggratisan swab test di puskesmas. Sayang, itu juga belum cukup karena dikhususkan untuk warga yang melakukan kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Seperti yang Trubus katakan, gratis saja tak cukup, tapi juga harus membuka seluas-luasnya akses swab test kepada masyarakat.
"Mereka yang di-testing karena hasil tracing dilakukan secara gratis. Kalau ada warga ingin melakukan testing karena ingin tahu untuk dirinya sendiri jangan pakai uang pajak," kata Anies dalam sebuah diskusi virtual 24 November lalu, seperti dikutip CNNIndonesia.
Anies mengatakan warga yang tidak pernah kontak erat dengan pasien COVID-19 bisa melakukan testing mandiri di rumah sakit swasta. Tapi biayanya ditanggung sendiri.
Tarif gratis memungkinkan
Pandemi, kata Trubus seharusnya memang sepenuhnya jadi urusan pemerintah. "UU Nomor 6 tahun 2018 jelas sekali mengatur bahwa urusan kekarantinaan adalah urusan pemerintah pusat," katanya.
Belum lagi, kata Trubus, bila merujuk "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tentang Kesehatan dan Keppres Nomor 12 tentang COVID-19 sebagai bencana nasional, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah," jelasnya.
Itu artinya tidak lagi pengecualian untuk mendapatkan tes COVID-19 secara gratis. "Karena dengan adanya tarif, maka yang terjadi kemudian kita lamban dalam hal penanganan COVID-nya," kata Trubus.
BACA JUGA:
Lalu, akan muncul pertanyaan, "apakah uangnya tersedia?" Kata Trubus, uang untuk menggratiskan tes COVID-19 semestinya ada dan harus ada. Khususnya di DKI Jakarta yang paling banyak catatkan kasus virus corona baru.
Trubus bilang, dalam APBD DKI Jakarta yang disusun untuk 2021, anggaran yang digelontorkan untuk gaji anggota dewan saja diusulkan mencapai Rp8 milyar per tahun. Itu berarti jika uang untuk gaji anggota dewan saja begitu besar, seharusnya untuk menanggulangi pandemi, khususnya untuk menggratiskan tes, bisa tersedia.
"Artinya, duit itu ada. Orang mereka mengajukan, berarti dia tahu di situ ada duitnya," ungkap Trubus.
Namun menurut Trubus selama ini tidak banyak masyarakat yang tahu pengelolaan anggaran tersebut. "Pengelolaan anggaran COVID-19 juga sampai sekarang enggak transparan," pungkasnya. Sebuah persoalan yang juga harus kita soroti ke depan.