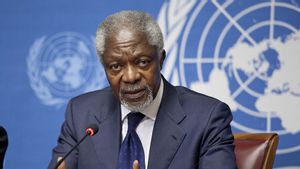JAKARTA - Eksistensi kelompok oposisi kerap dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, apalagi. Kelompok oposisi dapat meredam monopoli kekuasaan ala pemerintah zalim. Peran itu dilanggengkan dengan baik oleh ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU).
Nyali NU memilih posisi berseberangan dengan Soeharto dan Orde Baru (Orba) tak perlu diragukan. Segala macam kebijakan Orba yang mengganggu kemaslahatan rakyat Indonesia ditentangnya mati-matian. Dari penyalagunaan kekuasaan hingga penggusuran.
Relasi penguasa dan oposisi mutlak dibutuhkan. Posisi keduanya sama-sama mulia dalam suatu kehidupan bernegara. Oposisi dapat melanggengkan fungsinya sebagai penjaga pemerintah dari monopoli kekuasaan. Tujuannya supaya pemerintah dapat menjalankan kuasanya dalam koridor yang benar.
Potret itu pernah diterapkan oleh NU. Ormas Islam itu kerap memilih posisi berseberangan dengan pemerintah di era Orde Baru. NU tak dapat bekerja dengan narasi Asal Bapak Senang (ABS). Mereka kerap melanggengkan kritik kepada ragam kebijakan pemerintah. Utamanya yang memiliki muatan menyengsarakan rakyat Indonesia.
NU bak memahami bahwa nyali mereka jadi oposisi penuh dengan konsekuensi. Semuanya terbukti kala Orba merasa jalan politik kelompok agama seperti NU harus direduksi. Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang besar dipaksa Orba bergabung dengan partai kecil lainnya untuk jadi bagian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973.

NU pun tak gentar. Apalagi wakil NU dengan jubah PPP banyak bertengger jadi wakil rakyat. Perlawanan terhadap rezim zalim Orba terus berlanjut. Alih-alih perlawanan melemah, kritik yang dilemparkan NU kian keras. NU mulai mengecam tindakan Orba yang ingin menggoyang atau mengatur umat Islam.
NU berani melakukan walk out (keluar) di tengah persidangan DPR kala pembahasan mulai menganggu umat Islam. Antara lain pada 1978 dan 1980. Mereka tak ingin meloloskan aturan yang justru bertentangan dengan ajaran Islam.
Kondisi itu membuat Orba berang. Ruang politik simpatisan NU dalam PPP mulai direduksi. Empunya kuasa mulai mengambil alih PPP. Orba pun juga melanggengkan label bahwa NU bak memiliki agenda menolak frasa Pancasila dalam kehidupan bernegara. Suatu ajian andalan Orba yang menyalagunakan Pancasila untuk memukul mundur lawan politik atau kelompok oposisi.
“Pada awal 1980-an, rezim memaksa NU mengambil pilihan yang jelas antara oposisi atau akomodasi. Dalam sebuah pidato yang keras pada tahun 1980, Soeharto menyerang semua kelompok di tanah air yang tampak memusuhi Pancasila (versi Orba) dan justru berpegang kepada ideologi-ideologi saingannya, seperti komunisme, marhaenisme, atau agama dan dia mengancam akan menurunkan militer untuk memukul mereka.”
“Pidato ini jelas dialamatkan kepada tindakan walk out NU, sebagai peringatan tidak ada lagi toleransi untuk perlawanan terhadap ideologi resmi. Pada tahun-tahun berikutnya, Soeharto berulangkali mengulangi tema pembicaraan yang sama: kesetiaan kepada ideologi-ideologi selain Pancasila sama dengan tindakan subversi,” terang Ahmad Muhajir dalam buku Idham Chalid: Guru Politik Orang NU (2007).
Oposisi Orba
Perjuangan NU jadi oposisi tak hanya dilanggengkan dalam membela agama saja. NU juga kerap melanggengkan dukungannya terhadap hajat hidup orang banyak. NU mampu berdiri di atas semua golongan dengan frasa kemanusiaan.
Barang siapa yang mengganggu kemaslahatan rakyat Indonesia, NU siap berdiri menentangnya. Semua itu dilanggengkan dalam rangka membangun keadilan sosial dan demokrasi. Sekalipun mendapatkan tentangan Orba.
Ambil contoh, kala Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 1984-1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membela warga korban proyek stategis Waduk Kedung Ombo pada 1980-an.

Gus Dur dan NU tak gentar melemparkan kritik terbuka terhadap kebijakan rezim penguasa. Kritik yang dilanggengkan menggunakan dua ruang sekaligus. Ruang publik dan media massa. NU pun memberikan dukungannya kepada aktivis-aktivis lainnya yang ikut menolak.
Apalagi, dalam kasus Kedung Ombo Orba digambarkan tak adil dalam pembebasan lahan di tiga kabupaten (Boyolali, Grobogan, Sragen). Penentangan terhadap Orba terus berlangsung hingga Soeharto dan Orba berada di ujung tanduk kekuasaan pada 1998.
Sederet ulama NU pun meminta Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, jika Soeharto terus memaksa berkuasa yang muncul bukan lagi manfaat, tapi mudarat. Keberanian NU mengambil posisi berseberangan dengan Orba kemudian dikenang bak 'ornamen' penting sejarah bangsa Indonesia.
BACA JUGA:
“Misalnya, Gus Dur bersuara lantang dalam kritiknya terhadap bagaimana pemerintah daerah menangani kontroversi proyek waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah yang didanai oleh Bank Dunia. la juga secara kuat membela minoritas etnis dan agama di Indonesia. Namun demikian, ia juga bersusah payah mempertahankan hubungan baik dengan presiden.”
“Semula, pendekatan konstruktif ini bernilai baik dan Soeharto tampaknya menyambut baik sejumlah inisiatif Gus Dur. Menjelang Pemilu 1987, Gus Dur menjadi makin kritis terhadap PPP, yang kini banyak didominasi oleh kaum modernis. Sebagai akibatnya, ia menerima kemarahan banyak kalangan konservatif dalam NU, yang menyesali keluarnya organisasi keagamaan ini dari PPP, dan justru telah berbuat banyak untuk mempererat hubungan baiknya dengan Soeharto,” tutup Greg Burton dalam buku Biografi Gus Dur (2013).