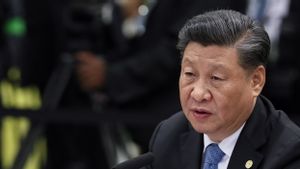JAKARTA - Lelah dengan segala pembatasan, protokol kesehatan, dan situasi serba tak pasti, sejumlah negara, terutama di Eropa, menyerah dan memilih hidup berdampingan saja dengan COVID-19. Sejumlah negara di Eropa itu antara lain: Denmark, Norwegia, Austria, Inggris, Perancis, Irlandia, Swedia, dan Swiss. Di Asia Tenggara, Singapura memilih strategi itu. Bagi mereka, enough is enough.
Dua tahun sudah seluruh dunia jungkir balik melawan COVID-19. Belum selesai urusan varian Delta, muncul varian Omicron. Entah varian apa lagi yang akan menyusul. Vaksinasi digenjot demi mencapai kekebalan komunal agar mempan melawan varian apa pun. Vaksinasi sudah, kebijakan pembatasan pun sudah ketat. Akan tetapi, COVID-19 seakan tak mau pergi.
Pemerintah Singapura pada hari Kamis 17 Februari 2022 mengumumkan memberlakukan bebas karantina kepada orang-orang yang datang dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Hong Kong. Selain itu, Singapura juga memberlakukan gelembung perjalanan dengan 24 negara yang antara lain ialah Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura juga memberlakukan sistem Jalur Perjalanan Tervaksin (VTL) dengan dua pulau di Indonesia, yakni Batam dan Bintan. Orang-orang yang datang ke Singapura melalui angkutan laut dari kedua pulau tersebut tidak perlu melakukan tes cepat berbasis antigen selama tujuh hari sebelum melakukan perjalanan. Masa karantina mereka juga dikurangi dari 14 hari menjadi tujuh hari.
“Kita tidak bisa berlama-lama lagi menutup perbatasan. Harus ada cara bagi Singapura untuk mengembangkan sistem hidup di tengah pandemi COVID-19 tanpa mengorbankan kesiagaan maupun kebutuhan ekonomi,” kata Menteri Perhubungan Singapura, S Iswaran.
Negara-Negara G-7
Sementara itu, di Jepang, Perdana Menteri Fumio Kishida akan mengumumkan kebijakan terkait pengendoran perbatasan pada pukul 19.00 waktu setempat atau pukul 17.00 waktu Jakarta. Keputusan Jepang menutup perbatasan mereka berdampak kepada ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pemerintah Jepang menghadapi kritik dari pelaku ekonomi, perguruan tinggi, dan institusi perawat lansia akibat penutupan perbatasan. Oleh sebab itu, Jepang memutuskan untuk melakukan pengendoran perbatasan yang terkendali. Rencananya, kuota kedatangan dari luar negeri akan dinaikkan dari 3.500 orang per hari menjadi 5.000 orang per hari.
Dibandingkan dengan negara-negara maju maupun kelompok tujuh negara terkaya dunia (G-7), Jepang sangat lambat dalam proses pemberian vaksin dan dosis penguat. Baru 11 persen penduduk Jepang yang diberi dosis penguat. Bandingkan dengan tetangganya, Korea Selatan, yang telah mencapai angka 50 persen.
Sementara itu Denmark meyakini, COVID-19 sudah mencapai puncaknya dan lebih dari 60 persen penduduk sudah divaksin ketiga. Angka cakupan vaksinasi ini lebih besar ketimbang negara-negara Uni Eropa lainnya yang rata-rata baru 45 persen. Ditambah dengan mereka yang pernah positif COVID-19, kira-kira 80 persen warga Denmark sudah memiliki kekebalan terhadap COVID-19.
Tanpa kebijakan pembatasan, tanggung jawab bergeser pada setiap individu. Jika merasakan gejala dan positif COVID-19, warga diimbau dengan kesadaran sendiri melakukan isolasi mandiri di rumah selama 4-5 hari.
Strategi serupa diambil Inggris. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan, sudah saatnya Inggris belajar hidup berdampingan dengan COVID-19 setelah tiga kali memberlakukan kebijakan penguncian wilayah (lockdown) secara nasional. Sebagai catatan, meski kebijakan sudah ketat, jumlah kematian di negara itu mencapai 159.000 orang.

Belajar hidup bersama COVID-19 berarti, pelancong yang sudah divaksin boleh masuk Inggris tanpa perlu tes COVID-19 lagi. Tetapi, mereka yang belum divaksin masih harus menjalani tes COVID-19 saat keberangkatan dan ketibaan. Bagi Inggris, yang penting program vaksin penguat (booster) sudah digenjot (84,6 persen penduduk sudah divaksin), stok obat COVID-19 terjamin, dan varian Omicron tak segalak Delta sehingga kematian bisa dicegah.
Strategi Denmark dan Inggris juga dilakukan Swedia sama persis. Naik moda transportasi umum tak perlu lagi mengenakan masker. Orang tak perlu lagi menunjukkan bukti vaksinasi saat mau masuk ke gedung mana pun.
Akan tetapi, strategi ”hidup bersama virus” terpaksa dipilih karena biaya tes COVID-19 masih dianggap terlalu mahal. Swedia mengeluarkan biaya hingga 55 juta dollar AS atau sekitar Rp789 miliar setiap pekan untuk tes COVID-19 saja. Karena sudah lebih dari 90 persen dari total 8,6 juta jiwa penduduk Swedia yang sudah divaksin atau sembuh dari COVID-19, langkah berani itu pun diambil.
Di Norwegia, meski 91 persen penduduknya sudah divaksin, masker tetap wajib dikenakan di angkutan umum dan pertokoan atau di lokasi yang sulit menjaga jarak fisik dengan orang lain.
Belum Berakhir
Melihat banyak negara memilih hidup bersama virus, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) khawatir, langkah itu terlalu dini. Padahal, pandemi belum berakhir dan belum jadi endemi. COVID-19 masih akan terus berevolusi dan bermutasi sehingga varian-varian baru pasti akan bermunculan dan menyebar ke seluruh dunia.
Namun, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengakui, dunia bisa saja lepas dari fase darurat pandemi jika target vaksinasi 70 persen populasi di setiap negara tercapai tahun ini.
BACA JUGA:
Ketua Kedaruratan WHO, Mike Ryan juga meminta setiap negara membuat rencana atau strategi keluar dari pandemi masing-masing dan tidak asal ikut-ikutan negara lain mencabut pembatasan. Pasalnya, setiap negara pasti menghadapi situasi yang berbeda. Negara yang hendak membuka diri kembali sebaiknya harus memastikan bakal mampu kembali memberlakukan kebijakan pembatasan dengan cepat jika kondisi memburuk.
Kekhawatiran WHO beralasan. Subvarian Omicron, yang ditengarai mampu menyebar lebih cepat ketimbang Omicron, sudah dideteksi beredar di 57 negara.
Perkembangan COVID-19 tidak bisa diprediksi. Sulit diketahui varian apa lagi yang akan muncul, bagaimana caranya, dan apa dampaknya. Situasi serba tak pasti kini menjadi bagian dari keseharian. Meski begitu, tidak kemudian berarti kita menyerah.
Bagaimana dengan Indonesia?
Pada awal-awal pandemi di Indonesia, bahkan jauh sebelum munculnya vaksin efektif untuk COVID-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meramalkan soal kondisi hidup berdamai dengan virus ini.
"Ada kemungkinan (kasus) masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata Jokowi, dalam siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis 7 Mei 2020.

Namun akibat kasus yang fluktuatif, Pemerintah Indonesia memunculkan wacana New Normal, yang juga berkembang di banyak negara. Inilah cikal bakal munculnya rencana hidup berdampingan dengan virus SARS-Cov-2
Dikutip dari VOA Indonesia, Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, hidup berdampingan dengan virus corona harus menjadi tujuan dan dipersiapkan oleh semua negara. Hal ini penting untuk dilakukan, karena kemungkinan COVID-19 bisa menjadi endemik sangat besar. Endemik sendiri artinya sebuah penyakit yang akan ada bersamaan dengan manusia dalam jangka waktu yang lama, yakni bisa lebih dari lima tahun. Maka dari itu, kata Dicky, kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sektor lainnya harus bisa berjalan berdampingan dengan corona tanpa munculnya kasus-kasus wabah atau kejadian luar biasa.