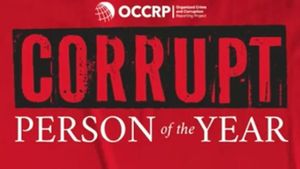JAKARTA - Kisruh mengenai keberadaan TikTok Shop menjadi headline di hampir semua media nasional dalam beberapa pekan ke belakang. Ramainya pemberitaan soal TikTok Shop berbarengan dengan keluhan para pedagang di Pasar Tanah Abang yang mengaku dagangannya sepi.
Kemudian, TikTok Shop dianggap sebagai penyebab menurunnya omzet pedagang di Pasar Tanah Abang dan pasar-pasar konvensional lain pada umumnya.
Pemerintah tidak tinggal diam. Demi menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah resmi melarang praktik perdagangan secara daring lewat platform media sosial atau yang kemudian kita sebut social commerce. Platform social media tidak boleh digabungkan dengan e-commerce, begitu singkatnya
Aturan tersebut tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dikeluarkan pada Selasa, 26 September lalu.
Social Commerce
Istilah social commerce bagi sebagian orang mungkin baru sering terdengar akhir-akhir ini, seiring masifnya pemberitaan mengenai TikTok Shop. Padahal, istilah social commerce sebenarnya sudah ada sejak sejak sekitar satu atau dua tahun terakhir.
Secara sederhana, social commerce adalah penggunaan platform media sosial untuk menjual jasa atau produk. Model penjualan social commerce bersifat end-to-end di mana pelanggan dapat melakukan transaksi tanpa meninggalkan aplikasi media sosial, dan tanpa memaksa pelanggan untuk berpindah platform.
Beberapa media sosial telah mendesain aplikasi mereka untuk memfasilitasi kebutuhan brand untuk melasanakan social commerce. Di antaranya adalah Facebook Shop, Instagram Shop, dan TikTok Shop.
Mengapa kemudian social commerce ini dianggap sebagai sebuah ancaman bagi pedagang konvensional, padahal sebelumnya juga sudah ada e-commerce?
Pertama, karena media sosial kini menjadi salah satu tempat di mana masyarakat banyak menghabiskan waktu mereka. Menurut DATAREPORTAL, 167 juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 29 jam per user per bulan di TikTok. Angka ini hanya kalah dari WhatsApp, di mana per user menghabiskan waktu 29 jam 6 menit per bulan.

Kedua, karena e-commerce dan social commerce memiliki sifat yang berbeda jika dilihat dari sisi konsumen. Sebagaimana dituturkan pengamat ekonomi Fithra Faisal Hastiadi, interaksi synchronous social commerce jauh lebih diminati ketimbang asynchronous ala e-commerce.
Dalam hal ini, e-commerce bersifat asynchronous karena konsumen tidak dapat melakukan empat hal yang disukai dalam waktu bersamaan untuk melakukan kegiatan belanja. Padahal menurut Fithra, ada empat faktor yang dibutuhkan konsumen saat berbelanja. Empat faktor tersebut adalah melihat penjual, melihat barang yang akan dibeli, kegiatan tawar-menawar, dan memegang barang yang diminati.
“Pada social commerce sifatnya synchronous. Dari sisi konsumen ini sangat diminati, karena konsumen bisa melihat penjual, melihat barang (bukan hanya katalog), dan ada pula yang bisa ditawar. Ini sudah lebih dari cukup untuk menarik konsumen berbelanja melalui social commerce,” kata Fithra saat berbincang dengan VOI.
“Dari sisi konsumen, ini sangat diuntungkan. Selain harganya yang lebih murah, gap surplus konsumennya juga lebih besar,” ujar Fithra menambahkan.
Tak hanya dari sisi konsumen, Fithra melihat social commerce ini juga sebenarnya menguntungkan sisi penjual karena mereka bisa lebih banyak mendapatkan produk untuk dijual.
BACA JUGA:
“Padagang di pasar juga kan bisa live. Dari Instagram bisa live. Jadi sebenarnya dari sisi UMKM terbantu juga dengan social commerce ini,” imbuh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tersebut.
Selain itu, di social commerce juga lebih mudah dalam melakukan transaksi. Karena sistem transaksi social commerce adalah dengan langsung menerima pembayaran konsumen. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, konsumen di social commerce tidak perlu berpindah platform untuk melakukan transaksi.
Predatory Pricing
Seiring dengan ramainya pemberitaan soal TikTok Shop, istilah predatory pricing juga ikut dikenal masyarakat. Pasalnya, TikTok Shop dituding melakukan predatory pricing sehingga berkontribusi melemahkan pedagang konvensional.
Fithra memberikan alasannya mengapa predatory pricing bisa memberikan harga yang sangat murah.
“Kita bicara secara umum, bukan hanya TikTok Shop. Jadi, pretadory pricing adalah menetapkan harga semurah-murahnya di bawah harga pasar, sehingga memakan kompetitor, memakan pasar, seperti predator,” ujar Fithra menjelaskan.
“Mengapa bisa melakukan predatory pricing? Itu karena dia sudah memiliki modal yang cukup besar, struktur yang sudah mapan, yang sudah sangat efisien. Sehingga secara langsung memakan pasar lain. Beberapa platform bahkan ini didukung pemerintahnya, struktur permodalannya didukung pemerintah sehingga bisa memberikan harga sangat murah,” kata Fithra lagi.
Namun, praktik predatory pricing yang dituduhkan kepada TikTok Shop ini dibantah oleh pengamat ekonomi digital, Ignatius Untung Surapati. Menurut Untung, TikTok Shop tidak melakukan predatory pricing, melainkan memberikan subsidi berupa voucher.
"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow 'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat, 15 September lalu.

Selain itu, Untung menjelaskan bahwa sejumlah platform e-commerce menarik pengguna baru dengan memberikan subsidi harga, biasanya berupa iming-iming voucher.
"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.
Lalu, apakah pedagang di Pasar Tanah Abang dan pasar konvensional sepi karena keberadaan TikTok Shop? Fithra dengan tegas menjawab tidak selalu. Alih-alih mengambinghitamkan TikTok Shop, ia menunjuk daya beli masyarakat sebagai salah satu penyebabnya.
“TikTok Shop itu saingannya adalah e-commerce, seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Mengapa pasar konvensional sepi, ya karena daya beli masyarakat memang rendah, utamanya sejak pandemi kemarin,” ujar Fithra menjelaskan.
“Banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga ini sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat,” kata Fithra berpendapat.