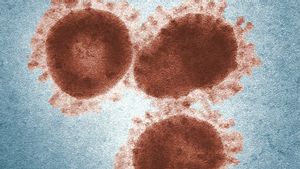JAKARTA - Secara resmi, pandemi COVID-19 tercatat masuk Indonesia pada awal Maret. Tak sedikit yang ragu akan hal itu. Beberapa ahli memperkirakan virus telah masuk sebelum kasus 01 dan 02 di Depok, Jawa Barat. Namun, bagaimanapun, yang jelas pemerintah telah melakukan banyak kesalahan dalam langkah pencegahan. Kita gagal belajar, bahkan dari salah satu wabah terbesar yang pernah kita alami: kolera.
Epidemiologis Harvard Profesor Marc Lipsitch membuat pemodelan yang menyimpulkan COVID-19 masuk ke Indonesia lebih awal dari pengumuman otoritas. Dari dalam negeri, staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono bahkan merinci COVID-19 telah masuk ke Indonesia sejak Januari.
Ini bukan kali pertama. Pada abad 19 di zaman kolonial, kala wabah kolera menyerang Hindia-Belanda, seorang sejarawan bernama Anthony Reid menentang keras banyak pernyataan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu hal yang paling disoroti Reid adalah lambannya respons pemerintah.
Dalam bukunya yang berjudul Asia Tenggara dalam Kurun Niaga jilid I (1988), Reid menulis, pemerintah kolonial sering kali lambat mendeteksi kehadiran sebuah wabah. “Kolera berat dalam bentuk asiatica atau morbus biasanya dipandang belum sampai ke Asia Tenggara sebelum pandemik parah tahun 1820-1822," tertulis.
Sejarah mencatat bagaimana pemerintahan di Nusantara, bahkan sejak dulu lamban mencegah dan menangani wabah. "Alasan-alasan bagi pandangan ini, sebagaimana halnya dengan pandangan-pandangan yang sama tentang wabah pes sebelum tahun 1911, tidak meyakinkan,” Reid, dalam tulisannya.
Reid menyimpulkan keterlambatan itu karena sumber sejarah Belanda mencatat pendiri Batavia, Jan Pieterszoon Coen meninggal karena menderita penyakit tropis yang diduga sebagai kolera pada 1629. Bagi Reid, jelas. wabah kolera telah masuk sebelum abad ke-19. Namun, karena pemukiman kala itu tak begitu padat, maka kolera sulit mewabah.
Mewabah
Awal mula kolera mulai mewabah secara masif, tak lain adalah saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels yang memerintah pada tahun 1808 hingga 1811 mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Oud Batavia --Batavia lama atau kawasan Kota Tua-- ke kawasan Nieuw Batavia Weltevreden, wilayah sekitar Lapangan Banteng.
Oleh Alwi Shahab, dalam bukunya Batavia Kota Hantu (2010), dijelaskan bahwa pemindahan dilakukan karena saat itu Oud Batavia dianggap sebagai sarang penyakit. “Pemindahan dilakukan karena pusat kota di tepi pantai itu telah menjadi sarang penyakit. Ada yang menyebutnya sebagai ‘kuburan’ orang Belanda.”
Untuk beberapa waktu, opsi tersebut dianggap tepat. Pemindahan dari kota rawan malaria ke tempat di mana persediaan air lebih baik. Namun, nyatanya, meski mendapat tempat tinggal lebih baik, ketidakpahaman mereka mengenai penyakit dan tak adanya obat menyebabkan banyak orang tetap terserang kolera. Tak terkecuali orang Eropa di Batavia.
Buku Sejarah Pemberantasan Penyakit di Indonesia (2007) yang dilansir dari Departemen Kesehatan RI menjelaskan kolera sebagai penyakit yang menyerang usus besar dengan gejala awal demam tinggi, kram perut, muntah, dan diare akut. Dengan segala gejala klinis itu, kolera menjadi penyakit yang mematikan jika tak segera diobati.
Senada dengan gejala di atas, kaum pribumi saat itu menyebut kolera sebagai penyakit muntaber (muntah berak). Sementara, orang Belanda menyebut kolera dengan istilah "bort". Sementara, orang inggris menyebutnya dengan pelafalan "kolera".
Berkembangnya wabah tersebut disinyalir karena lingkungan kotor dan sanitasi yang buruk. Salah satu penyebabnya, tak lain adalah banyaknya rumah di Batavia yang belum memiliki kakus atau kamar mandi. Segala limbah dan kotoran langsung mengalir ke kanal-kanal. Kondisi kanal kala itu diperparah dengan buangan limbah pabrik penyulingan arak dan penggilingan tebu. Alhasil, kanal begitu bau dan berlumpur.
Maka, tak mengherankan bila kolera menyebabkan kepanikan besar bagi orang Eropa di Batavia. Apalagi, saat mengetahui gambaran ganasnya kolera kala itu. Tingkat fatalitas wabah kolera pada 1821 dijelaskan dalam catatan pegawai kolonial urusan pribumi, Roorda Van Eysinga yang berjudul Verschillende Reizen en Lotgevallen (1830).
“Ada hari-hari ketika di Batavia terdapat 160 orang mati (akibat kolera). Mereka mengalami kejang-kejang hebat dan meninggal dunia beberapa saat kemudian … Saya beruntung tidak terjangkit dan melihat banyak pasien saya kembali sehat. Namun, saya kelelahan hingga hampir tidak dapat terus bekerja,” tulis Roorda.
“Dalam iklim yang sangat panas ini, sulit sekali merawat pasien kelas sosial rendah yang biasanya tinggal di ruangan kecil berdinding bata. Ruangan itu harus ditutup rapat untuk mencegah adanya aliran udara. Kemudian, pasien-pasien harus dimandikan dengan air hangat. Saya menginstruksikan agar para penderita digosok dengan arak dan terkadang saya melakukannya sendiri jika kekurangan orang,” tambahnya.
BACA JUGA:
Alhasil, kolera yang dianggap penyakit baru memancing respons tak lazim dari masyarakat, baik pribumi dan mereka keturunan Tionghoa --dua sebutan umum bagi dua kelompok masyarakat yang mendominasi populasi Batavia kala itu. Susan Abeyasekere, dalam bukunya yang sempat dicekal pada zaman Orde Baru, Jakarta: A History (1989), mengungkap baik pribumi maupun orang Tionghoa banyak yang memercayai hal-hal berbau magis untuk melawan kolera.
“Orang-orang Indonesia yang individualis mengandalkan ‘air suci’ yaitu air yang berasal dari lokasi kramat atau telah dibacakan doa oleh pemuka agama islam. Ada pula yang mengadakan ritual massal untuk mengusir penyakit.”
Berbeda dengan orang Tionghoa, cara mereka yang tak lazim adalah memanggil barongsai untuk berkeliling pecinan jika terdapat ancaman wabah kolera. “Mereka percaya bahwa setan penyebar kolera takut pada barongsai,” tutup Susan.