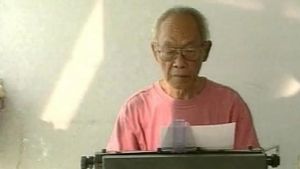JAKARTA – Sejarah hari ini, 104 tahun yang lalu, 17 Juli 1919, pemerintah kolonial Hindia Belanda meresmikan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mangunjayan. Peresmian rumah sakit yang menjadi cikal Bakal Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta dilakukan untuk mengobati penderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Surakarta.
Sebelumnya, penanganan ODGJ tak pernah serius. Empunya kuasa kemudian berpikir memperbanyak RSJ. Upaya itu dilanggengkan supaya urusan pengobatan penyakit jiwa ditangani dalam satu tempat dan serius.
Perang dan wabah adalah dua hal yang membuat angka ODGJ tumbuh subur di Nusantara. Beratnya hidup di masa perang dan wabah, apalagi di bawah penjajahan Belanda jadi muaranya. Kesusahan hidup itu membuat banyak di antara rakyat Hindia Belanda – utamanya kaum bumiputra—jadi ODGJ.
Masalah itu tak pernah ditanggapi secara serius sekalipun mulai marak. Utamanya, oleh kaum bumiputra. Mereka menganggap urusan ODGJ tak berkaitan dengan dunia medis. Banyak yang meyakini penyebab ODGJ adalah kehadiran roh jahat atau diguna-guna.
Penanganan ODGJ kemudian menggunakan jasa paranormal, dibanding tenaga kesehatan. Alih-alih ODGJ sembuh, ritual yang dilakukan justru membuat mereka kesakitan. Semuanya karena ritual yang dilanggengkan mengutamakan siksaan fisik: dipukul atau ditendang.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda tak jauh beda. ODGJ awalnya dianggap penyakit biasa. Semuanya berubah ketika perang dan wabah semakin marak hadir Nusantara. Belanda yang awal tak merasa memiliki tanggung jawab mulai ikut campur.
Belanda meminta rumah sakit milik militer untuk membuat ruangan khusus untuk pasien penyakit jiwa. Hasilnya tak berjalan mulus. Pasien-pasien penyakit jiwa bak bukan dirawat, tapi ditahan. Kesembuhan ODGJ pun jadi hal yang paling mustahil diraih.
Belanda pun tak mau meneruskan tren buruk itu. Mereka ingin berubah. Ide pembangunan tempat khusus merawat ODGJ pun muncul. Rumah Sakit Jiwa, namanya.
“Kemudian dibuka pula rumah-rumah sakit di Banten dan di Semarang; bahkan pada tahun 1800-an, sebuah rumah sakit jiwa dibuka di Bogor. Di sini kelihatan bahwa semua itu lebih bersifat ‘pengurungan’ daripada perawatan.”
“Kalaupun hal itu memang merupakan sesuatu yang baru dipandang dari sudut mentalitas (gagasan memisahkan penderita dari masyakaratnya tidak dapat begitu saja diterima di Jawa, bahkan hingga saat ini). Dapat dibayangkan bahwa dampaknya benar-benar teraupetik hampir nihil,” ungkap sejarawan Denys Lombard dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan (1996).

Ide membangun RSJ terus langgeng. Pemerintah Belanda pun mulai menggalakkan pembangunan RSJ di berbagai daerah di Nusantara. Semuanya supaya urusan penyakit jiwa dapat ditangani di satu tempat. Pun tidak memenuhi rumah sakit.
Pembangunan doorgangshuis voor krankzinnigen di Solo (Surakarta), misalnya. Belanda melihat Solo sebagai kota yang butuh peran rumah sakit yang kemudian dikenal sebagai RSJ Mangunjayan. Keinginan itu kemudian bertambah kuat dengan dukungan jajaran penjajah Belanda yang bertugas di Solo.
Alhasil, RSJ Mangunjayan diresmikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 17 Juli 1919. Belanda percaya kehadiran RSJ Mangujayan dapat membuat penangan ODGJ dapat maksimal. Apalagi, kapasitas RSJ Mangunjayan digadang-gadang dapat menampung ratusan orang. Kini, RSJ Mangunjayan telah berpindah lokasi dan berubah nama menjadi RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta (lebih dikenal dengan nama RSJD Surakarta).
BACA JUGA:
“Dibangun dan diresmikan sebagai doorgangshuis voor krankzinnigen oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 17 Juli 1919. Dikenal kemudian oleh masyarakat sebagai Rumah Sakit Jiwa Mangunjayan. Rumah sakit ini terletak di areal seluas 0,69 hektar, dengan kapasitas 216 tempat tidur di JI. Bhayangkara no. 50, Solo.”
“Pada 1986, Pemerintah Daerah Surakarta melakukan ruislag (tukar guling). Mereka kemudian membangun dan memindahkan rumah sakit di atas lahan seluas 20.995 meter persegi di tepian Sungai Bengawan Solo dengan kapasitas 293 tempat tidur,” terang Denny Thong dalam buku Memanusiakan Manusia (2013).