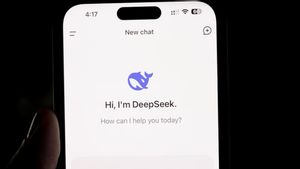JAKARTA – Pro kontra nyamuk wolbachia masih berlanjut. Sampai sekarang, efektivitas wolbachia menekan penularan demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi pertanyaan. Ditambah edukasi kepada masyarakat dinilai masih kurang, sehingga perluasan penggunaan teknologi wolbachia masih terhambat.
Usaha pemerintah dalam memerangi DBD melalui berbagai program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dinilai belum efektif. Karena itu dikembangkan strategi pendamping untuk mengenalikan kasus DBD, salah satunya adalah dengan teknologi wolbachia.

Tapi perlu diingat bahwa teknologi wolbachia bukan satu-satunya cara untuk mengatasi kasus DBD. Perlu harmoninasi antara penggunaan teknologi wolbachia dan metode pengendalian lainnya sehingga teknologi ini dapat memberikan dampak maksimal.
Nyamuk wolbachia meningkat popularitasnya dalam beberapa pekan terakhir, puncaknya setelah warga di Bali menolak pelepasan telur nyamuk tersebut. Minimnya informasi dianggap sebagai salah satu alasan mengapa warga di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng menolak pelepasan nyamuk berwolbachia.
Peningkatan Kasus DBD
Isu miring seputar teknologi wolbachia justru lebih cepat menyebar luas di kalangan masyarakat. Kekhawatiran akan kembali terjadinya pandemi, pemicu Japanese Encephalitis, sampai penularan LGBT termasuk di antara penyebab nyamuk wolbachia banyak ditolak.
Namun, mantan Sekretaris Jenderal Kemenkes Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS menekankan pentingnya penerapan teknologi wolbachia sebagai upaya penanggulangan DBD.
Dokter Supriyanto menilai, demam berdarah masih menjadi masalah di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan sejak 2012-2015 menunjukkan bahwa jumlah kasus DBD mengalami peningkatan dari 90.245 sampai 129.500 kasus. Setahun kemudian kembali terjadi lonjakan drastis, menjadi 204.171 kasus.
Setelah itu, angka kasus DBD mengalami naik turun, namun pada 2022 kasusnya tercatat sebanyak 143.184. Pada periode Januari – Juli 2023, sebanyak 42.690 orang terinfeksi DBD dan 317 orang meninggal.

“Artinya ini adalah hal yang sangat serius dan berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan teknologi wolbachia ini,” kata Dr. Supriyantoro dalam webinar Indonesia Healthcare Forum bertajuk Pro dan Kontrak Nyamuk Wolbachia: Mana yang Benar?
Sejak pertama kali ditemukan pada 1968 di Surabaya, kasus DBD terus menyebar ke kampir seluruh wilayah di Indonesia. Sejak saat itu pula pemerintah terus berupaya melakukan pengendalian DBD dengan mengandalkan program pemberantasan sarang nyamuk (PSN).
Namun, program tersebut dinilai belum bisa mengendalikan DBD secara maksimal.
Sampai akhirnya tercetuslah penyebaran nyamuk wolbachia seperti yang dilakukan sejumlah negara lain seperti Brasil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Meksiko, Kiribati, Kaledonia Baru, dan Sri Lanka.
Sukses di Yogyakarta
Uji coba penyebaran nyamuk wolbachia pertama kali dilakukan di Yogyakarta pada 2016 lalu. Sejak program ini dimulai, angka kasus DBD di Kota Yogyakarta berangsur menurun, dan pada tahun 2023 mencatat rekor terendah di angka 67 kasus, demikian mengutip laman UGM.
Riset terkait nyamuk wolbachia di Indonesia dilakukan oleh World Mosquito Programe (WMP) Yogyakarta, yang merupakan kolaborasi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Monash University, dan Yayasan Tahija.
Peneliti utama WMP Prof. Adi Utarini mengklaim penelitian yang dilakukan timnya berhasil mendapat rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Ia juga memastikan tidak ada efek samping dari penggunaan nyamuk wolbachia.

“Nyamuk wolbachia itu aman. Tidak ada transmisi horizontal wolbachia pada nyamuk aedes aegypti ke serangga lain,” tegas wanita yang akrab disapa Prof. Uut ini.
Prof. Utarini juga memastikan bahwa tidak akan ada infeksi wolbachia dari nyamuk aedes aegypti ke manusia. Tak hanya itu, pelepasan nyamuk aedes aegypti wolbachia tidak mengubah populasi nyamuk.
“Nyamuk ber-wolbachi juga memiliki karakter yang sama dengan nyamuk di alam, termasuk dalam hal resistensi insektisida,” Prof. Uut menambahkan.
Tantangan Perluasan Teknologi Wolbachia
Namun, terlepas dari keberhasilan teknologi wolbachia di Yogyakarta, publik tidak begitu saja langsung mempercayai teknologi tersebut. Masih banyak masyarakat yang menolak penggunaan nyamuk wolbachia untuk mengatasi DBD. Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Dr. Tjandra Aditama, Dp.P(K) meng-highlight empat hal yang membuat perluasan teknologi wolbachia masih terkendala.
Menurut Tjandra, salah satu kendalanya adalah biaya yang besar untuk produksi nyamuk dalam jumlah yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan. Selain itu, teknologi wolbachia juga belum mendapat rekomendasi dari WHO.
Menurutnya, sejauh ini WHO hanya mengapresiasi keberhasilan nyamuk wolbachia namun belum merekomendasikan untuk melakukan perluasan di wilayah lain.

“Hasil penelian Prof Uut diapresiasi dan bahkan diterima oleh Vector Control Advisory Group (VCAG) WHO, namun perlu dicatat bahwa VCAG belum merekomendasikan hal ini kepada WHO untuk penggunaan secara luas, tapi yang direkomendasikan adalah membuat guideline process selanjutnya,” tegas Tjandra.
“Jadi sederhananya, teknologi wolbachia ini belum dapat rekomendasi dari WHO,” imbuhnya.
Selain itu, Tjandra juga memaklumi masih banyaknya masyarakat yang menolak nyamuk wolbachia untuk mengendalikan kasus DBD. Ia menyarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dampak jangka panjangnya jika ingin diimplementasikan secara luas.
BACA JUGA:
Terakhir, Tjandra menegaskan bahwa teknologi wolbachia bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan DBD.
“Memang ini ada hasilnya, tapi bukan silver bullet, bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, sehingga pengendalian secara terintegrasi tetap harus dilakukan," ujar Tjandra memungkasi.