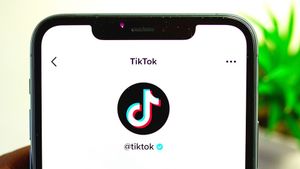JAKARTA - Sejak zaman dulu, dukun beranak sudah berjasa bagi persalinan wanita bumiputra. Mereka dianggap penyelamat. Eksistensinya pun mahsyur di Nusantara. Tapi bangsa Eropa memandang sebaliknya. Alih-alih dianggap memberi bermanfaat, kehadiran mereka justru membawa mudarat. Mereka dianggap berkontribusi meningkatkan angka kematian bayi. Sampai-sampai Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, menggagas program pelatihan untuk “mencerahkannya”.
Jauh sebelum kehadiran bidan, dukun beranak adalah orang penting yang membantu persalinan wanita bumiputra. Kepercayaan itu muncul secara turun-temurun, pun pemandangan itu masih banyak terjadi di masa penjajahan Belanda. Karena dianggap sakti, dan mematok tarif rendah sampai bisa dibayar dengan hasil bumi, dukun beranak begitu disukai wanita bumiputra.
Salah satu potretnya bisa dilihat di Banda Aceh. Profesi ini banyak dilakoni kaum wanita. Biasanya, wanita tersebut sudah pernah melahirkan dan memiliki kesaktian tertentu, utamanya yang punya “koneksi” dengan roh leluhur yang dikenal dengan nama Nek atau Nek Rabi.
Dikisahkan, Nek Rabi adalah roh seorang perempuan yang dahulu bertempat tinggal di Banda Aceh. Pada suatu malam waktu dia pulang dari pengajian, ada orang yang memenggal kepalanya karena disangka mencuri. Si pembunuh membawa kepalanya ke suatu tempat bernama Indrapuri dan menguburnya di situ, sedang tubuhnya di kubur di Banda Aceh. Karena Nek Rabi dikenal sebagai pribadi yang baik, rohnya sering membantu dukun beranak dalam proses persalinan.

“Karena Nek Rabi mati sebelum saat yang ditentukan maka dia berkelana dan selalu meminta sesuatu pada wanita yang sedang melahirkan. Tetapi Nek Rabi hanya muncul jika ada yang tidak wajar dilakukan pada upacara-upacara sebelum kelahiran khususnya pada kenduri bulan ketujuh. Pada peristiwa begitu dia ‘'memasuki’ jiwa dukun beranak, yang lalu berbicara dengan suara roh Nek Rabi dan dukun itu tidak mampu lagi melanjutkan bantuannya dalam persalinan itu,” ungkap Antropolog T. O. Ihromi dalam Pokok-Pokok Antropologi Budaya (1999).
Tak cuma bagi masyarakat Aceh, pengaruh besar dukun beranak juga muncul dari masyarakat Bugis, Sulawesi sejak masa lampau. Budayawan Feby Triadi, menyebut dukun (sanro) beranak atau sanro makkiana hanya terbatas kepada mereka yang memiliki garis keturunan. Oleh sebab itu, peran sandro makkiana menjadi kesohor di kalangan masyarakat Bugis.
Belum lagi perihal kehebatan yang menyebar dari mulut ke mulut yang dapat melegitimasi kemampuan dari sanro makkiana. Antara lain mereka memiliki kekuatan seperti mantra atau benda-benda tertentu. Berkat itu, masyarakat mempercayai seorang sanro makkina mampu mendatangkan kekuatan tertentu. Utamanya, untuk menolong wanita Bugis yang akan melahirkan.
“Termasuk jika dulu setelah Islam menguat, ada perilaku-perilaku istimewa yang dilakukan si sanro ini, termasuk melaksanakan sholat sebelum dan sesudah menolong orang yang melahirkan. Atau hanya memberikan bacaan-bacaan tertentu di air yang nantinya akan diberikan bagi orang yang akan beranak, berkat hal itu (mereka dipercaya) mampu melancarkan si ibu hamil untuk melahirkan,” ungkap Feby Triadi saat dihubungi VOI, 24 Juni.

Melanggengkan angka kematian
Boleh jadi dukun beranak menjadi begitu kesohor dalam melakukan persalinan wanita bumiputra. Kendati demikian, pemerintah kolonial Belanda dan dokter Eropa memiliki anggapan buruk akan dukun beranak. Penyebabnya, kebanyakkan dukun beranak tak memiliki pengetahuan mempuni terkait proses alami kelahiran bayi normal. Lebih lagi, dukun beranak digambarkan tak sepenuhnya paham kondisi-kondisi menyimpang saat membantu persalinan. Alhasil, dukun beranak melanggengkan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi.
Sebagai solusi, pemerintah kolonial di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) memberikan pelatihan kepada dukun beranak. Namun, upaya itu angin-anginan. Beberapa dukun beranak memang ada yang termotivasi untuk belajar. Sedang, lainnya kembali kepada pengetahuan lelulur yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Kondisi itu seperti yang terjadi di Minahasa, Sulawesi. Yang mana, angka kematian bayi tak menurun.
“Walaupun sejak tahun 1854 dukun beranak yang disebut Biang di Minahasa telah diberikan kursus pendidikan ilmu kesehatan oleh Gubernemen, tetapi pada tahun 1885 tingkat kematian bayi dan kematian ibu yang melahirkan sangat tinggi,” tulis Jessy Wenas dalam Sejarah dan kebudayaan Minahasa (2007).
Pemerintah kolonial tak menyerah. Atas rekomendasi dari Kepala Kesehatan pemerintah kolonial Belanda, Dr. W. Bosh, sekolah kebidanan yang pertama didirikan di Batavia pada 1852. Tapi, sekolah tersebut senasib dengan pelatihan bagi dukun beranak, yakni berakhir dengan kegagalan. Penyebabnya tak lain karena pamor dukun beranak melampau mereka yang berprofesi sebagai bidan. Bersamaan dengan itu angka kematian bayi masih meninggi, sekalipun bidan dan dukun beranak bersinergi membantu persalinan masyarakat.
“Bila dibandingkan dengan angka kematian akibat cacar, angka kematian ibu bersalin sebenarnya jauh lebih tinggi. Sayangnya. pemerintah Belanda kurang memperhatikan tingginya angka kematian itu. Baru tahun 1889 oleh Straats (ahli obstetri dari Austria) ilmu kebidanan diberikan dengan sukarela,” tutup Sudarwan Danim dkk dalam buku Kebidanan (2003).
*Baca Informasi lain soal SEJARAH atau baca tulisan menarik lain dari Detha Arya Tifada.