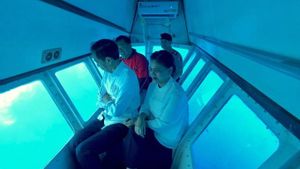JAKARTA - Masa awal kuasa maskapai dagang Belanda, VOC penuh kisah. Orang Belanda di pusat pemerintahan VOC Batavia pernah kekurangan populasi wanita Eropa. Hanya pejabat tinggi dan orang kaya saja yang boleh membawa istri Eropanya. Sedang kelas serdadu dan kelasi kapal tak akan mampu.
Kebanyakan orang Belanda pun memilih wanita lokal untuk dijadikan gundik. Nyai, namanya. Kehadiran nyai buat hasrat seksual orang Belanda tersalurkan. Tren hubungan gelap itu dikenal luas sebagai kumpul kebo.
Jan Pieterszoon Coen pernah dibuat pusing selama menjabat orang nomor satu VOC di Batavia. Pria yang menjabat Gubernur Jenderal VOC dua kali, 1619-1623 dan 1627-1629, itu khawatir dengan tingkah laku anak buahnya yang mulai jauh dari agama. Sebab, kebanyakkan orang Belanda di Batavia melanggengkan kegiatan asusila.
Mereka gemar ke pelacuran untuk memuaskan hasrat seksual. Coen yang dikenal sebagai ‘polisi moral’ marah besar. Ia pun menindak tegas pelaku asusila. Bahkan sampai diancam hukuman mati. Namun, ia segara menyadari pangkal masalahnya. Ketiadaan wanita Eropa jadi muaranya. Populasi wanita Eropa di Batavia sedikit – jika tak mau dikatakan kurang.

Coen berinisiatif untuk menyampaikan keluhannya kepada pimpinan pusat VOC, Heeren Zeventien. Peletak dasar kolonialisme di Nusantara itu mengungkap negeri koloni sedang kekurangan wanita. Ia meminta empunya kuasa segara mengirimkan wanita baik-baik ke Batavia. Supaya moral anak buahnya di Batavia terjaga.
Coen kesal. Ia lalu dengan tegas membumbui suratnya dengan menulis bahwa semua orang tahu kalau manusia tak bisa hidup tanpa perempuan baik-baik. Itupun kalau Heeren Zeventien ingin menciptakan pemukiman yang beradap di negeri koloni. Heeren Zeventien tak mengindahkannya. Wanita Eropa yang datang cuma segelintir.
“Karena persediaan wanita Eropa terbatas, maka para pegawai VOC dan penduduk laki-laki Eropa Kota Batavia harus mencari pasangan dari perempuan-perempuan lokal. Namun, lagi-lagi hukum VOC ikut campur tangan dengan tujuan untuk menjamin stabilitas koloni. Contohnya tidak boleh ada pegawai VOC diperbolehkan kembali ke Eropa sebelum menetap selama lima tahun dihitung sejak tanggal pernikahannya. “
“Setelah 1633, peraturan tersebut ditambahkan dengan tidak diperbolehkannya seorang suami pergi ke Eropa tanpa meninggalkan uang yang cukup banyak untuk istrinya. Tidak seorang pun, yang sudah menikah atau lajang, boleh kembali ke negaranya tanpa izin tertulis dari gubernur jenderal. Lebih jauh lagi, penduduk kota harus tinggal setidaknya tiga tahun di permukiman dan membayar di muka ongkos kepulangan,” ungkap Jean Gelman Taylor dalam buku Kehidupan Sosial di Batavia (2009).
Kumpul Kebo
Selepas Coen tak menjabat, pegawai lokal mengambil jalan pintas. Mereka paham benar jika warisan dari Coen melarang adanya perkawinan antara orang Eropa dan wanita lokal. Karenanya, orang Belanda memilih melakukan hubungan gelap dengan wanita lokal, utamanya mereka yang berstatus budak. Alias kumpul kebo.
Orang Belanda banyak menjadikan wanita muda atau paruh baya sebagai gudik. Orang-orang menyebut wanita yang bekerja kepada orang Belanda itu sebagai nyai. Seorang nyai memiliki banyak tugas. Segala macam urusan rumah adalah tanggung jawabnya.
Tanggung jawab lain yang tak kalah penting adalah memuaskan tuannya perihal urusan ranjang. Akan tetapi, seorang nyai kebanyakan tak dinikahi oleh orang Belanda. Mereka Cuma dua sejoli yang hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan.
Aktivitas kumpul kebo pun jadi tren populer. Gereja bahkan tak bisa memutus mata rantai kumpul kebo umatnya. Padahal Coen semasa hidupnya telah mengingatkan berkali-kali pergundikan adalah muasal hancurnya moral. Sebab, pergundikan dapat dapat menyebabkan hal negatif. Dari aborsi hingga penelantaran anak.

Apalagi anak hasil pergundikan tidak diakui secara agama. Pun secara kehidupan bermasyakarat anak hasil hubungan gelap itu dianggap sebuah aib. Tapi, nasib seorang nyai tak sepenuhnya suram. Banyak di antara nyai dipercaya oleh tuannya untuk memiliki beberapa budak belian untuk menunjang kehidupan. Dalam artian, kehidupannya serba kecukupan. Sekalipun tanpa status pernikahan.
“Nyai, bila kita menyebutkan kata ini pada masa kolonial, reaksi orang akan beragam. Mungkin ada yang tersenyum kecut, memasang wajah sinis, atau tertawa terbahak-bahak. Tentu saja nyai pada masa itu, tak lepas dari urusan dapur dan kasur, alias teman tidur bagi para pria Eropa kesepian di tanah surga ini. Sebutan nyai pada masa kolonial ditujukan pada wanita muda, setengah baya, yang menjadi gundik, wanita simpanan, orang asing, khususnya orang Eropa.”
“Sebutan ini menurut anggapan orang Eropa pada masa itu setara dengan concubine, bijwijf, atau selir yang meniru kebiasaan para raja yang memiliki banyak selir. Walau sebenarnya sebutan nyai pada masa itu adalah eufemisme bagi para bediende atau baboe yang diangkat sebagai istri gelap para tuan kolonial. Agar tak memalukan sang tuan, para nyai didandani. Mereka diajari beretiket dan berbahasa Belanda, menikmati budaya Eropa,” ungkap Achmad Sunjayadi dalam buku [Bukan] Tabu di Nusantara (2018).