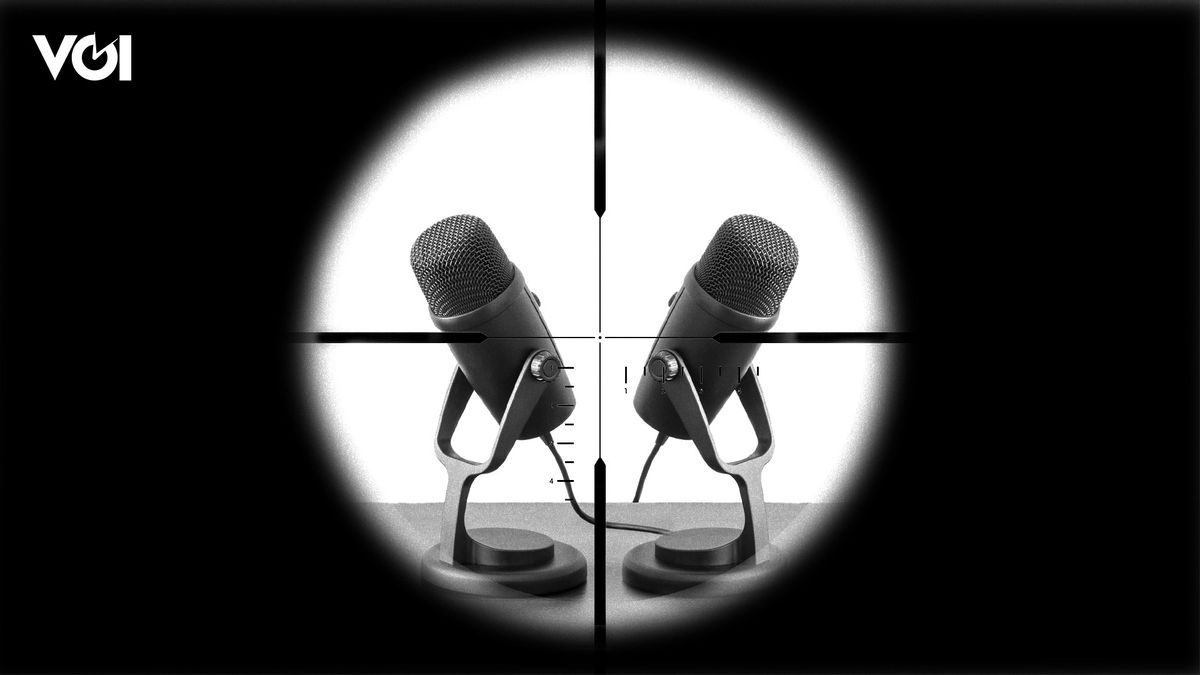JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran memantik kontroversi belakangan ini. Berbagai organisasi jurnalis, mulai IJTI, AJI, PWI hingga Dewan Pers melontarkan kritik karena dianggap melarang penayangan jurnalisme investigasi secara eksklusif dalam salah satu pasalnya.
Padahal jika membaca secara keseluruhan draft RUU Penyiaran yang beredar di publik, masih ada kontroversi lain, karena dinilai mengambil wewenang yang sudah diatur dalam peraturan perundangan lain. Dengan kata lain, banyak materi dalam draft RUU Penyiaran yang bertabrakan dengan UU lain.
Pasal 34F ayat (2) draft RUU Penyiaran menyebutkan bahwa penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau plarform teknologi penyiaran lainnya wajib melakukan verifikasi konten siaran ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Isi Siaran (SIS).
Dengan adanya pasal tersebut, maka RUU Penyiaran juga mengatur penyelenggaraan platform digital penyiaran. Artinya, pembuat konten yang memiliki dan menjalani akun media sosial seperti Youtube, TikTok juga masuk dalam ranah RUU Penyiaran ini.
BACA JUGA:
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar. Menurutnya, bila membaca rumusan draft yang sekarang disusun oleh DPR, pengaturan revisi UU penyiaran akan menjangkau platform digital.
“Termasuk konten-konten yang didistribusikan melalui platform berbasis user generated content atau UGC, seperti Youtube, TikTok dan sebagainya,” ujarnya Senin, 20 Mei 2024.
Pengaturan tersebut dinilai overlapping dengan pengaturan dalam undang-undang lain. Sebab, saat ini pengaturan platform berbasis UGC seperti Youtube, TikTok dan sebagainya mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Bahkan jika merujuk PP No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maupun Permenkominfo No 5 tahun 2020, sudah menjelaskan pengaturan terhadap konten-konten yang didistribusikan/ditransmisikan melalui platform berbasis UGC.
“Tentu bisa menjadi persoalan baru ketika konten yang didistribusikan melalui platform UGC itu disamakan dengan konten siaran,” tambah Wahyudi.
Dia menjelaskan, konten siaran dihasilkan oleh lembaga penyiaran seperti televisi, rumah produksi dan sebagainya. Sementara konten melalui platform UGC adalah konten yang diproduksi perseorangan atau pembuat konten dan kemudian didistribusikan melalui platform UGC.
RUU Penyiaran sebagai Dasar Hukum Pemantauan Platform Digital

Hal senada dilontarkan Ketum PWI, Hendry Ch Bangun yang mengakui bahwa draft RUU Penyiaran juga menyasar kebebasan para podcaster dalam membuat konten kreatifnya. Sebab, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan mengawasi beragam konten di platform media sosial.
“Yang disebut isi siaran di sini (RUU Penyiaran) nggak hanya di media massa. Tetapi juga individu, jadi podcaster ya kan. Misalnya orang melaporkan kecelakaan, ada darahnya, dan menurut KPI nih sadis misalnya begitu. Lalu akun dia diusulkan untuk dibekukan atau dihapus,” tuturnya.
Peneliti pusat studi media dan komunikasi Remotivi, Muhamad Heychael menambahkan, bila membaca draft, bisa ditafsirkan RUU Penyiaran akan diperluas ke ranah digital atau OTT yang berpotensi mengarah ke pembuat konten di berbagai platform termasuk YouTube, Google, Meta, dan sebagainya.
Hal ini bisa terlihat dari perluasan wewenang KPI untuk mengawasi konten-konten digital atau audio visual. Selain mempertanyakan kemampuan teknis KPI untuk melakukannya, Heychel menegaskan hal tersebut bisa dikatakan sebagai surveillance alias pemantauan.
“Mereka ini seolah-olah menempatkan apa yang terjadi di ranah digital seperti logika di media televisi atau penyiaran. Penyiaran itu menggunakan sumber daya publik. Berbeda dengan digital, itu sifatnya tidak serempak. Ini mau ditabrak. Konsekuensinya termasuk produk-produk jurnalistik yang ada di media digital. Ada juga pasal di mana KPI berwenang sebagai klarifikator konten. Ini lebih gila lagi,” terangnya.
Pakar komunikasi UI, Effendy Ghazali menilai penyusun draft RUU Penyiaran bisa saja sudah mengantisipasi kemungkinan perpindahan jurnalisme investigasi dari media penyiaran konvensional ke platform digital.
Dia mengungkapkan, untuk menyajikan sebuah jurnalisme investigasi diperlukan waktu yang lama, biaya yang cukup besar serta menguras energi. Tapi, belum tentu hasil jurnalisme investigasi tersebut bisa menarik keuntungan secara finansial bagi pemilik media.
“Kalau dari hasil ngobrol-ngobrol dengan jurnalis-jurnalis senior, sebenarnya jurnalisme investigasi tanpa dilarang penayangannya pun bisa “mati” dengan sendirinya karena berbagai faktor. Ini bisa kita lihat di jam berapa misalnya penayangan investigasi,” tuturnya.
“Nah sekarang mulai banyak tuh yang pindah ke platform digital, yang paling sering dapat sorotan sekarang kan Bocor Alus itu. Hal ini yang mungkin membuat RUU Penyiaran juga diperluas untuk mengawasi meski sudah ada UU ITE,” tambah Effendy.
Pengamat media Unair, Irfan Wahyudi menginterpretasikan berbagai larangan yang ada di draft RUU Penyiaran sebagai wujud pembungkaman pers dan ekspresi media. Menurutnya, peraturan itu membingungkan dan menimbulkan keresahan publik. Sebagai wujud penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, RUU Penyiaran memang perlu disesuaikan dengan zaman.
Dalam perjalanannya, Irfan meninjau dua regulasi yang mengatur masalah penyiaran. Pertama, Keputusan Presiden dalam Omnibus Law, yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran. Kedua, UU ITE atau peraturan penyiaran dari KPI. Kini, RUU penyiaran juga mengatur hal yang sama.
“Permasalahannya terletak pada draft RUU penyiaran yang memiliki fungsi serupa dengan UU ITE dalam implementasinya. Sehingga, antara UU ITE dan RUU Penyiaran ini saling tumpang tindih dan memicu kebingungan,” tukasnya.
Irfan menegaskan, draft RUU Penyiaran yang ada saat ini berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi dan bahkan mempidanakan konten yang dianggap meresahkan, bukan hanya dari media, tetapi juga para pembuat konten di platform digital.