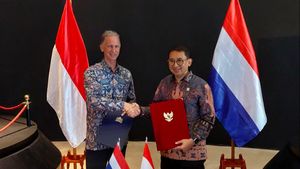JAKARTA - World Health Organization (WHO) telah mengklasifikasikan keraguan banyak orang akan penggunaan vaksin sebagai sepuluh ancaman terbesar kesehatan global di tahun 2019. Artinya, keraguan pada penggunaan vaksin sama bahayanya dengan HIV AIDS, polusi udara, hingga demam berdarah.
Di Indonesia, keraguan ini cukup besar. Sebagian penolakan dilakukan sebagai protes pada perusahaan farmasi. Lainnya menganggap vaksin tak alami atau diragukan kehalalannya. Keraguan akan penggunaan vaksin sejatinya sudah terjadi sejak lama. Memutar jauh ke belakang kala Jakarta masih Batavia dan Indonesia masih bernama Hindia Belanda, gelagat antivaksin sudah timbul.
Kala itu, wabah cacar muncul sebagai salah satu penyakit paling mematikan. Uniknya, kebanyakan yang menolak bukan cuma penduduk asli, tapi juga orang-orang keturunan Eropa atau keturunan campuran (mestizo). Saat masuk ke Batavia pada 1644, penyakit cacar adalah momok yang amat menakutkan. Saking asingnya, penduduk menganggap cacar sebagai ulah makhluk halus.
Hal wajar memang. Pasalnya, saat itu hanya sedikit orang yang dapat bertahan dari serangan cacar, meski beberapa golongan macam budak dari Bugis dan Bali memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat ketimbang para budak dari Nias. “Nias terpapar cacar lebih jarang dibanding Bali dan Bugis sehingga punya daya imun lebih rendah,” ungkap Peter Boomgard dalam "Smallpox, Vaccination, and the Pax Neerlandica".
Lebih rinci, Iksaka Banu dalam kumpulan cerpen yang dituang ke buku berjudul "Teh dan Pengkhianat" menjelaskan bagaimana variola --virus penyebab cacar yang juga jadi nama lain cacar-- pada abad ke-14 muncul bak malaikat pencabut nyawa. Kisah itu ia gambarkan dalam cerpen berjudul Variona. Saat itu, Bali, Ternate, dan Ambon jadi daerah yang paling kerap dilanda kematian akibat cacar. Di Bali saja, angka kematiannya mencapai 18 ribu orang, terhitung menjelang akhir tahun 1871.

Pertanyaan soal vaksin
Saat itu, satu-satunya cara agar wabah dapat teratasi adalah dengan mengirimkan vaksin dari Belanda. Namun, tentu saja langkah itu memakan banyak waktu. Laju penyebaran wabah di Bali terlampau lebih cepat.
Akhirnya, vaksin diproduksi di sejumlah wilayah Hindia Belanda, mulai dari Madiun, Kedu, hingga Kediri. Namun, lagi-lagi, upaya itu tak mampu menghadapi laju penyebaran wabah. Akhirnya, sebuah solusi diambil. Otoritas mencari anak yatim piatu di Batavia untuk dikirim ke Bali.
Vaksin disuntikkan ke dalam tubuh anak itu untuk kemudian dipanen bagi banyak orang di Bali. Langkah itu langsung ditolak oleh pihak panti asuhan. "Sadarkah bahwa di sini tuan sebenarnya sedang berusaha mencampuri urusan Tuhan?" terkisah dalam halaman 51 buku.
Terkait segala penolakan pada vaksin, Jean Gelman Taylor dalam buku "Kehidupan Sosial di Batavia" menceritakan bagaimana vaksin dianggap sebagai perlawanan terhadap pengobatan kuno. “Imunisasi terhadap cacar adalah perlawanan terhadap pengobatan Indonesia dan mestizo yang menggabungkan pengobatan dengan hal-hal yang berbau spiritual magis,” tertulis.
Pendiri Rumah Vaksin Dokter Piprim Basarah Yanuarso menyebut vaksinasi sebagai metode pencegahan penyakit. Ia turut mengungkap pandangannya terkait gerakan antivaksin.
"Seruan antivaksin bukan main-main bisa bikin wabah bermunculan ke mana-mana. Kalau orang tua yang galau ini sampai 40 persen dari populasi wabah bisa bangkit kembali," tuturnya dikutip Detik.com, Senin, 13 Januari.
Meski begitu, sejatinya masih banyak pertanyaan yang meliputi penggunaan vaksin. Soal landasan hukum yang menjamin keamanan vaksin, misalnya. Hingga saat ini, belum ada peraturan atau UU yang mengatur bahwa otoritas akan menjamin sejumlah langkah ketika vaksinasi menyebabkan gangguan medis tertentu pada seseorang.

Selain itu, soal kandungan detail pada vaksin, misalnya. Hingga saat ini, kandungan rinci pada vaksin masih jadi pertanyaan. Hal ini berkaitan dengan kejelasan halal dan haram penggunaan vaksin. Bagi penduduk mayoritas Islam, otoritas tentu harus mampu memberikan jaminan halal.
Sejauh ini, satu-satunya halal dan haram vaksin hanya bisa kita pelajari dari kontroversi yang muncul terkait vaksin measles rubella (MR). Kala itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa bernomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII) untuk Imunisasi.
Ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Hasanuddin AF jelas menyebut vaksin MR mengandung unsur haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Namun, saat itu Komisi Fatwa MUI memperbolehkan penggunaan vaksin MR dengan alasan darurat syar'iyyah lantaran belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Alasan ini, di saat yang sama memunculkan kebingungan. Sebab, subjektivitas amat bermain dalam penentuan kondisi keterpaksaan dan darurat syar'iyyah.