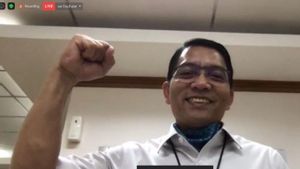JAKARTA - Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) menilai rancangan rencana investasi dan kebijakan komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) masih berpihak setengah hati pada upaya transisi energi yang berkeadilan.
Hal ini dilatarbelakangi minimnya target pensiun dini PLTU dalam draf rencana ini dan berpotensi memperlambat langkah reformasi sistem energi Indonesia menjadi lebih hijau dan ambisius.
Direktur Eksekutif dan Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, dokumen CIPP JETP masih cukup kontradiktif.
Menurutnya, target bauran energi terbarukan dalam CIPP cukup ambisius yakni mencapai 44 persen pada 2030.
Namun di sisi lain, hanya dua PLTU yang masuk daftar pensiun dini dalam skema ini yaitu PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon.
“Sebagian PLTU yang masuk pensiun dini, yakni PLTU Cirebon-1 sebenarnya sudah masuk dalam skema energy transition mechanism (ETM). Jadi seolah tidak ada niatan untuk benar-benar melakukan penutupan PLTU batu bara. JETP menjadi tidak jelas, awalnya mau pensiun PLTU batu bara justru tidak dilakukan dengan serius,” ujarnya dalam kerangan kepada media, Selasa 21 November.
Sementara itu, Direktur Program Transisi Bersih Harryadin Mahardika menambahkan, hal yang sama pernah dilakukan Indonesia.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diterbitkan pada 2014, Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan 23 persen pada 2023 dan 31 persen pada 2050.
Namun pada saat yang sama, Indonesia juga memulai Program 35 Gigawatt (GW) yang mayoritas adalah PLTU batu bara.
Penambahan PLTU akhirnya justru menggerus ruang pengembangan energi terbarukan, sehingga target bauran energi hijau tidak tercapai.
“Dalam dokumen CIPP, PLTU captive tidak dimasukkan. Padahal, pertumbuhannya sangat tinggi dari 1,3 GW pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, dan masih terus bertambah. Hal ini akan menjadi penghalang besar yang dapat menggagalkan target nol emisi Indonesia seperti sebelumnya. Meski target CIPP tercapai 100 persen, target nol emisi Indonesia tidak akan pernah tercapai lantaran PLTU captive akan tetap hasilkan emisi dalam jumlah besar,” jelas Harryandi.
Di sisi lain, Arise! Indonesia, Dian Sunardi juga mengaku kecewa dengan adanya usulan teknologi solusi palsu dalam dokumen CIPP, seperti co-firing biomassa.
Pasalnya, solusi palsu terbukti tidak akan efektif dalam mengurangi emisi.
Bahkan, adanya solusi palsu justru memperkaya segelintir individu-oligarki, mempromosikan privatisasi dan komodifikasi sumber daya ekologis, dan membebaskan korporasi yang berkontribusi terhadap krisis iklim (polluters) dari tanggung jawabnya.
“Dan yang paling penting, malah akan memperparah krisis iklim dan merusak masa depan transisi energi Indonesia. Indonesia harus mengambil sikap tegas, menyatakan tidak pada solusi palsu dan mengeluarkannya dari CIPP,” tegas Dian.
Koalisi CSO juga menyoroti porsi utang dan hibah dalam dana JETP. Bhima menyebut pendanaan dari negara maju atau International Partners Group (IPG) sangat tidak menjunjung prinsip berkeadilan. Utamanya, Amerika Serikat yang jumlah pinjaman non-konsensionalnya sangat besar. Hal ini berarti Indonesia akan menanggung pinjaman dengan bunga pasar.
“Apa fungsinya menunggu dokumen CIPP JETP dirilis kalau kesepakatan dengan negara maju hanya biasa saja, masih pinjaman yang sifatnya business as usual?” kata Bhima.
Koordinator Perkumpulan AEER Pius Ginting menyatakan, Sekretariat JETP dan Pemerintah Indonesia harus berjuang meningkatkan porsi hibah dalam pendanaan JETP.
Jepang sebagai anggota IPG perlu meningkatkan tanggung jawab pendanaan dalam bentuk hibah, mengingat perannya dalam investasi PLTU di Indonesia, sebagai pasar ekspor batu bara, dan kontribusi pada emisi sektor transportasi di mana sebagian besar kendaraan yang ada di pasar masih terkait investasi Jepang.
“Sikap yang lebih baik diberikan oleh Jerman dengan mengalokasikan 167 juta dolar AS dalam bentuk hibah atau technical assistance atau 10 persen dari jumlah pendanaan publik oleh Jerman. Porsi jumlah hibah ini juga seharusnya menjadi acuan bagi negara IPG lainnya sebagai pelaksanaan dari prinsip common but differentiated responsibility dalam pendanaan mengatasi planet yang kian mendidih panas,” tegasnya.
Tak hanya itu, Bhima menggarisbawahi absennya berbagai reformasi kebijakan fiskal dan moneter untuk segera diimplementasikan. Padahal, JETP diharapkan membawa perubahan kerangka kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung percepatan pensiun PLTU batu bara.
“Kami belum melihat langkah teknis yang dibutuhkan untuk menggeser insentif fiskal pada sektor pertambangan dan migas untuk membuat bisnis fosil secara ekonomis kurang menarik dibandingkan energi terbarukan. Dari segi perpajakan juga tidak tersentuh, maka JETP ini justru menunjukkan silo-silo pembahasan yang belum komprehensif. Waktu untuk revisi CIPP JETP diharapkan menyatukan seluruh aspek kebijakan pemerintah yang harus dirubah secepatnya,” ungkap dia.
Perlu Memihak Masyarakat
Di sisi lain, Direktur Program Koaksi Indonesia Verena Puspawardani mengingatkan bahwa dokumen CIPP perlu terus dikawal agar menjadi rekomendasi yang kuat bagi Satuan Tugas Transisi Energi Nasional.
Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, dan merangkul pemerintah daerah dalam mengelola transisi energi berkeadilan dengan pemetaan kebijakan hingga ke tingkat daerah.
Selain itu, penerapan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) juga harus menjadi landasan yang memprioritaskan beragam kelompok rentan dan komunitas terdampak.
BACA JUGA:
Dokumen CIPP, kata dia, juga mengakui bahwa transisi energi akan mendorong terciptanya pekerjaan hijau (green jobs), serta memperhitungkan potensi lapangan kerja yang hilang dan langkah mitigasinya.
Untuk itu, lanjut dia, peningkatan kapasitas pekerja menjadi penting agar tetap dapat terserap di ekosistem energi terbarukan.
Selain itu, sektor industri lain perlu dikembangkan untuk mengurangi dampak meningkatnya pengangguran baru.
“Terkait green jobs, pemerintah telah memiliki inisiatif memajukan green jobs dengan adanya peta jalan. Hal ini perlu dimasukkan ke dalam dokumen CIPP untuk memperkuat kebijakan nasional dan regional sehingga memastikan kebijakan tersebut dimanfaatkan,” tutur Verena.