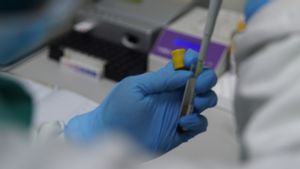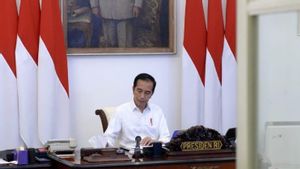JAKARTA - Carut marut penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 kembali mengemuka setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim bahwa, industi tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan alat perlindungan diri (APD). Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) menilai, hal ini karena ulah mafia alat kesehatan (alkes).
Ketua Umum IKATSI Suharno Rusdi menyebutkan, mafia impor alkes kembali berulah. Meraka melakukan penetrasi lobi untuk memasukkan barang impor sehingga kembali membuat industri TPT nasional gigit jari.
Rusdi menjelaskan, kapasitas garmen dan IKM konveksi yang mencapai 2,5 juta ton per tahun atau sekitar 600 juta potong per bulan sudah sangat bisa memenuhi kebutuhan APD terutama Hazmat dan Gown yang diperkirakan mencapai hanya 10 juta potong per bulan.
"Bahkan untuk bahan baku dari kain, benang hingga seratnya juga bisa kita bisa penuhi dari dalam negeri yang kapasitasnya rata-rata di atas 2,5 juta ton per tahun," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Senin 18 Mei.
Rusdi mengungkap, di tengah pandemi ini Kemenkes mempersyaratkan bahan baku spunbond non-woven agar impor dapat masuk dengan leluasa. Padahal bahan APD berbahan baku woven atau kain tenun yang dikembangkan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah dites dilab uji Balai Besar Tekstil (BBT) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Hasilnya sudah memenuhi standar Hazmat dan Gown dari WHO. Harganya pun lebih murah, dipakainya lebih aman dan nyaman.
Berdasarkan pengkajian keahlian tekstil di IKATSI, katanya, untuk water and blood penetration bahan woven dan non woven kemampuannya sama karena menggunakan teknologi coating atau laminasi yang sama. Namun bahan woven lebih tahan sobek, lentur dan breathable dibandingkan dengan bahan non-woven sehingga lebih aman dan nyaman ketika dipakai oleh tenaga kesehatan.
"Woven harganya jauh lebih murah, karena non-woven spunbond menggunakan bahan Polyprophilene yang harganya naik hampir 2 kali lipat karena digunakan juga sebagai bahan baku masker," jelasnya.
Rusdi menjelaskan bahwa kapasitas produksi non-woven nasional yang bisa disuplai ke APD hanya untuk sekitar 1 juta potong per bulan, kalau dari bahan woven kemampuan suplainya bisa lebih dari 375 juta potong APD per bulan.
BACA JUGA:
"Makanya jangan kaget kalau banyak produsen maksa untuk ekspor APD, karena stok di lokal banyak. Kalau ada produsen lokal yang klaim bisa suplai APD dari non-woven lebih dari 1 juta per bulan, harus diteliti lagi, karena pasti campur dengan APD impor, itu calo berkedok produsen yang punya izin produksi, izin edar, sekaligus izin impor," tuturnya.
Menurut Rusdi, kondisi ini sebagai jawaban dari Menteri BUMN tentang ketergantungan kita terhadap alkes impor, karena memang produsen lokal selalu dipojokkan oleh barang impor sehingga produsen enggan untuk melakukan produksi dan memilih menutup pabriknya.
"Begitu kuatnya penetrasi para mafia impor ini seharusnya jadi perhatian penegak hukum seperti kasus 27 kontainer tekstil di Batam" tuturnya.
Di samping itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengonfirmasi, bahwa pihaknya memproduksi APD khususnya Hazmat dan Gown atas arahan BNPB terkait standarnya agar memenuhi kriteria WHO.
Lebih lanjut, katanya, Anggota APSyFI juga sudah mensuplai serat, benang, hingga kain woven-nya, sedangkan anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memproduksi kain dan garmennya.
"Jadi dengan arahan dari BNPB, dari hulu ke hilir langsung kami kerjakan pembuatan APD sesuai standar WHO, karena kami dengar tenaga medis di lapangan kekurangan APD. Terlebih di gudang-gudang kami banyak stok kain dan benang jadi pengerjaannya lebih cepat," katanya.
Kecewa kepada Pemerintah
Saat ini beberapa anggota API dan APSyFI merasa kecewa karena pemerintah tidak menyerap produk APD yang mereka kerjakan dengan alasan memprioritaskan bahan non-woven spund bond yang hanya dapat satu kali pakai lalu dibuang.
"Padahal, d itengah pandemi COVID-19 ini, produksi APD bisa membantu kondisi keuangan perusahaan terutama untuk membayar gaji karyawan, walau pun ini hanya sekitar 3-5 persen dari total produksi yang biasa dilakukan dalam keadaan normal," jelasnya.
Di balik produksi APD ini juga ada ribuan tenaga kerja dan puluhan perusahaan yang terlibat. Redma mengatakan, 10 juta potong APD per bulan itu dikerjakan oleh 15 ribu orang di garmen, 10 ribu orang untuk produksi 30 juta meter kain, dan 7 ribu orang untuk produksi 2500 ton benang dan 5 ribu orang untuk produksi 2500 ton serat, jadi total 37 ribu tenaga kerja di sekitar 20 perusahaan.
"Kalau dipenuhi oleh impor, berapa tenaga kerja yang terlibat? Berapa devisa yang terbuang?," ucapnya.
Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Rizal Tanzil menyatakan, bahwa pihaknya masih berharap agar pemerintah dapat menyerap APD lokal. Karena meskipun hanya sekitar 5 persen dari produksi normal, setidaknya dapat menyerap tenaga kerja lokal yang sedang kesusahan di masa pandemi ini.
"Karena seharusnya prioritas penggunaan produk dalam negeri itu harus terimplementasi, bukan sekadar lips service saja," jelasnya.