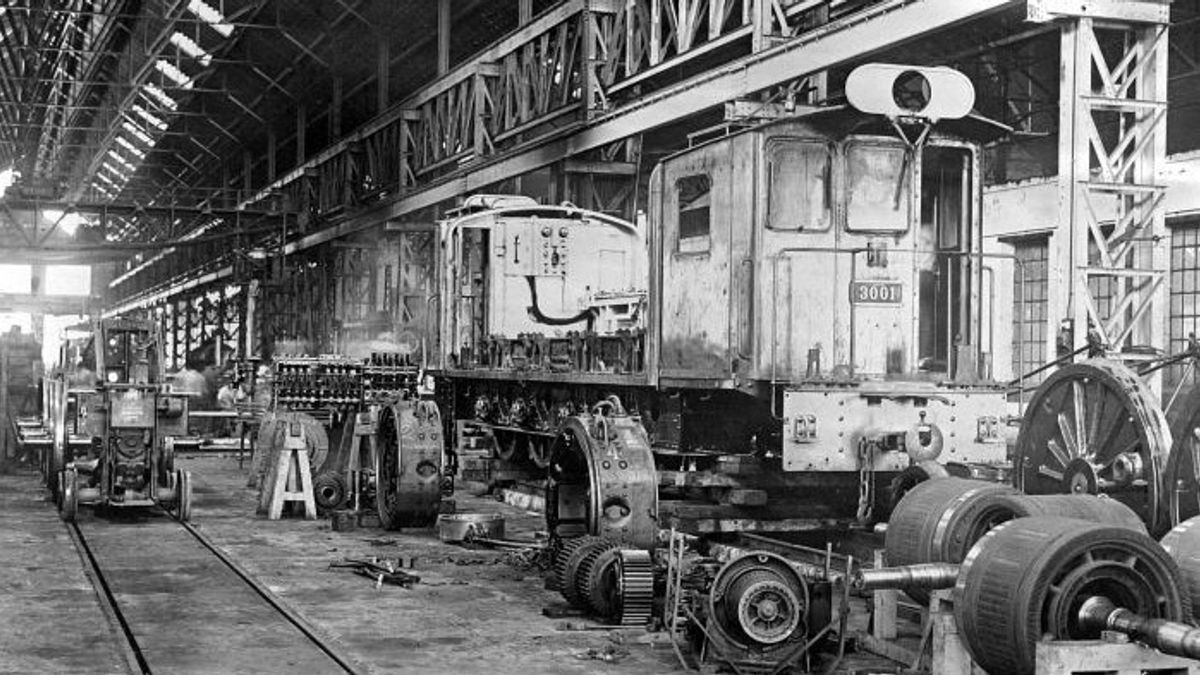
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) rampung dibahas. Pemerintah segera menyerahkan draf rancangannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kelas pekerja menolak keras lantaran dianggap mengancam hajat hidup mereka. Sadar tak sadar, negeri ini sedang mengulang masa ketika rakyat Indonesia hidup dan bekerja di bawah penjajahan Belanda.
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) membulatkan sejumlah poin mengkhawatirkan yang terkandung dalam RUU Cilaka. Pertama, RUU dinilai akan mengorbankan kesejahteraan dan mempreteli hak demokratis para pekerja. Kedua adalah soal keramahan pada investor yang dapat jadi pisau bermata dua. Kekhawatiran kedua jadi beralasan mengingat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang katanya siap "menggigit" penghalang investasi.
RUU Cilaka dapat mempermudah investor (perusahaan) untuk melakukan PHK massal. Status karyawan tetap makin jauh di angan. RUU Cilaka juga memberi ruang bagi investor untuk menindas lewat penghapusan pidana ketenagakerjaan. Dan yang tak kalah fundamental dari segalanya adalah penerapan upah per jam yang otomatis menghapus upah minimum.
Melirik beberapa poin terkandung, sekilas kita dapat melihat kemiripan kondisi dengan Indonesia di masa kolonial, ketika hajat hidup rakyatnya di bawah kuasa penjajah. Sebuah kolom di Majalah Tempo berjudul Gaji (dan Korupsi) Sepanjang Masa (1983) yang ditulis Ong Hok Ham menjelaskan pemikiran pemerintah kolonial yang kala itu menganggap uang negara dapat dialokasikan untuk perkara yang lebih penting dari membiayai para pegawai yang bekerja untuk mereka.
“Dan di situ negara sebenarnya menghadapi kesukaran kedua: menentukan jumlah riil yang sebenarnya diperlukan pejabat itu, sebab ada pejabat yang punya tugas politik dan harus hidup dengan gaya tertentu demi kewibawaannya. Di samping itu, di masyarakat seperti Indonesia masih ada persoalan keluarga besar: tidak saja istri dan anak, tapi juga saudara-saudara juga anak buah,” tertulis.
Ditarik jauh ke belakang, kondisi macam ini juga pernah ditemui di masa Kerajaan Mataram. Sebagai kerajaan tradisional, mereka tidak mengalokasikan harta raja untuk menggaji para pejabatnya. Harta raja ketika itu digunakan untuk kepentingan politis dan militer. Saat itu, para pejabat diberi kekuasaan atas rakyat. Dari kekuasaan itulah mereka menghasilkan uang.
Terpuruk karena 'maruk'
Maju ke akhir abad 18, majunya perekonomian dan kehadiran VOC membawa perubahan. Bukan perubahan yang teramat baik, sayangnya. Kala itu, jual beli jabatan dimulai. Jabatan-jabatan seperti bupati, demang, hingga bekel mulai jadi komoditas jual beli oleh raja atau pemegang lungguh (priayi) kepada mereka yang gila kuasa. Dikisahkan, jabatan bupati ketika itu dihargai 10 ribu real atau lebih.
“Harga tersebut harus dibayar sebelum jabatan diduduki. Komersialisasi semacam ini menolong keuangan negara, tapi merupakan beban besar di masyarakat. Sebab, semua pengawasan keuangan oleh pusat jadi lepas sama sekali."
Jual beli jabatan ini membuka peluang bagi siapa pun, asal mereka memiliki uang. Maka, keluarga pemberontak, pedagang China atau swasta Belanda pun menempati posisi-posisi tersebut. Hal ini berdampak pada nasib pekerja. Uang bicara semakin lantang. Posisi kuasa jadi samar. Pemerintah tak memiliki cukup kekuatan untuk mencampuri urusan pemilik modal dan pekerjanya, termasuk kala banyak keputusan yang tak memihak pekerja.
Karut-marut sistem itu turut menggerogoti VOC dari dalam. Sebagai empunya otak dari komersialisasi di atas, VOC justru mengalami kesulitan dalam menggaji pegawai. Padahal, kekuatan VOC kala itu sudah dianggap setara negara Batavia. Bayangkan, VOC dapat meminjam lebih banyak kepada raja-raja sekaligus menjadi cukong terbesar raja-raja di Indonesia.
Seiring waktu, penyakit itu kian nampak. VOC makin miskin ketika di waktu yang sama para pejabatnya semakin kaya. Kondisi ini sempat direkam Multatuli dalam karya momumentalnya, Max Havelaar. Mereka yang harusnya berdagang demi keuntungan majikan malah berusaha mengambil keuntungan sendiri.
Komentar keras dilayangkan Multatuli: Kurasa penting untuk mengharapkan agar mereka tidak berlagak congkak pada awal jabatan dan yang terutama tidak lamban serta apatis pada tahun-tahun terakhir pemerintahan mereka.
Investasi untuk siapa?
Meski begitu, ada sejumlah hal yang dapat ditiru dari sistem apresiasi pekerja di masa lampau. Soal proses cuti yang mulai diperkenalkan pada abad ke-19, misalnya. Jean Gelman Taylor, dalam buku Kehidupan Sosial di Batavia menceritakan bagaimana cuti kala itu amat dinanti-nanti para pegawai pemerintahan dan militer.
"Dengan diperkenalkan sistem cuti, maka pegawai pemerintah dan militer mendapat gaji ketika cuti selama dua tahun di Eropa. Jumlah uang pensiun yang ditambahkan juga memungkinkan mereka pensiun di Eropa. Sistem cuti tak hanya memberikan pemulihan secara fisik. Sistem itu juga memberikan semacam pembaharuan spiritual dan intelektual di tempat asalnya. Itu adalah cuti yang ditunggu dan juga direncanakan oleh pegawai,” tertulis.
Dari berbagai kisah di atas, pemerintah hari ini seharusnya dapat bercermin. Hati-hati dengan perkara yang dapat menjadikan riasan pemerintahan hari ini nampak teramat kolonial, meski perkara-perkara kolonial sekalipun memiliki sisi yang manusiawi.
Lagipula, pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak pernah mengamanatkan apapun soal investasi, kecuali yang bermanfaat bagi hajat hidup anak bangsa. Dengan kebijakan yang berpotensi mencekik pekerja lokal, bagaimana mungkin bicara soal manfaat bagi anak bangsa?
Dan jangan lupakan sajak W.S Rendra:
Ada yang bersenjata, ada yang terluka.
Ada yang duduk, ada yang diduduki.
Ada yang berlimpah, ada yang terkuras.
Dan kita di sini bertanya :
“Maksud baik saudara untuk siapa ?
Saudara berdiri di pihak yang mana ?








